Artikel

Belajar Untuk Menjadi Cerah Dan Bijak
23 Januari 2024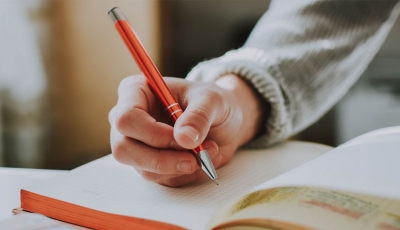
Menurut Saya.......
8 Januari 2024Oleh: Dr. Dr. Adi W. Gunawan, ST., MPd., CCH®
Seorang sahabat sedang menulis tesis dengan topik aplikasi hipnoterapi untuk depresi. Ia minta saran dan masukan saya, dan rujukan literatur yang akan digunakan dalam penyusunan tesisnya.
Salah satu pertanyaan penting yang ia tanyakan pada saya adalah tentang definisi hipnosis dan hipnoterapi.
Saya jelaskan bahwa setiap pakar, seturut pemahamannya, merumuskan definisinya sendiri. Dan ini bisa dipahami dari perspektif perkembangan keilmuan hipnosis dari waktu ke waktu yang terus mengalami kemajuan.
Definisi hipnosis oleh para pakar di tahun 1880an, 1900an awal, 1920 - 1950, 1950 - 1980an, dan di tahun 2000an walau secara prinsip ada kesamaan, terdapat nuansa berbeda. Masing-masing pakar tentu mendefinisikan hipnosis seturut pemahamannya. Saya sarankan ia mengutip definisi yang berasal dari para pakar hipnosis modern, karena ini yang paling relevan.
Selain itu, saya juga jelaskan bahwa definisi yang paling kuat dijadikan rujukan adalah yang dikeluarkan organisasi terkemuka, khususnya American Psychological Association (APA) Divisi 30, Society of Psychological Hypnosis.
APA adalah organisasi ilmiah dan profesional terkemuka di bidang psikologi di Amerika Serikat, beranggotakan lebih dari 146.000 peneliti, pendidik, dokter, konsultan, dan mahasiswa.
APA telah tiga kali merumuskan definisi hipnosis, tahun 1993, 2003, dan terakhir 2014, sebagai acuan para praktisi dan peneliti pengguna hipnosis dalam kegiatan mereka.
Menurut APA, 𝐡𝐢𝐩𝐧𝐨𝐬𝐢𝐬 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐨𝐧𝐝𝐢𝐬𝐢 𝐤𝐞𝐬𝐚𝐝𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐥𝐢𝐛𝐚𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐡𝐚𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐟𝐨𝐤𝐮𝐬 𝐝𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐫𝐤𝐮𝐫𝐚𝐧𝐠𝐧𝐲𝐚 𝐤𝐞𝐬𝐚𝐝𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐟𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐜𝐢𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐤𝐚𝐩𝐚𝐬𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩 𝐬𝐮𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢 (Elkins dkk, 2015, p.6). Dan 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐢 𝐡𝐢𝐩𝐧𝐨𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢 (𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐡𝐢𝐩𝐧𝐨𝐬𝐢𝐬 𝐤𝐥𝐢𝐧𝐢𝐬) 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐩𝐞𝐦𝐚𝐧𝐟𝐚𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐡𝐢𝐩𝐧𝐨𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐦𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐬 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐩𝐬𝐢𝐤𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐬 (p.7).
Saya mendefinisikan hipnosis sebagai kondisi kesadaran bercirikan pikiran sadar rileks, fungsi kritis analitis pikiran sadar menurun, disertai meningkatnya fokus dan konsentrasi, sehingga individu menjadi sangat responsif terhadap pesan atau informasi yang diberikan kepada pikiran bawah sadar (Gunawan, 2017).
AWGI dan APA Divisi 30 sama-sama menyatakan bahwa hipnosis adalah kondisi kesadaran, karena memang demikianlah adanya, sesuai dengan yang kami temukan dan alami di ruang praktik saat menangani klien di lebih dari 130.000 sesi konseling dan terapi.
Kondisi kesadaran ini bisa terjadi dan dialami individu secara alamiah, dan bisa juga dengan proses induksi, baik yang dilakukan oleh terapis pada klien (heterohipnosis), atau yang dilakukan sendiri (swahipnosis).
Sementara definisi hipnoterapi, menurut AWGI, adalah terapi, menggunakan teknik atau metode apa saja, yang dilakukan di dalam kondisi hipnosis, untuk mencapai tujuan terapeutik (Gunawan, 2017).
Hipnosis sebagai kondisi kesadaran divalidasi dengan pengukuran gelombang otak. Saya beruntung mendapat kesempatan belajar ke pakar hipnoterapi Tom Silver dan pakar meditasi Anna Wise.
Tom Silver selama lebih dari 20 tahun menggunakan mesin EEG khusus mengukur gelombang otak klien-kliennya. Tom bisa tahu dengan sangat akurat kondisi kedalaman hipnosis setiap kliennya berdasar pola dan komposisi gelombang otak yang tampil di layar komputernya.
Berdasar data ini, Tom mencipta teknik luar biasa yang memampukan ia untuk "mencabut" emosi langsung dari pikiran bawah sadar klien, tanpa harus memproses memori atau akar masalah. Teknik ini hanya bisa bekerja efektif di kedalaman hipnosis sangat spesifik. Saya beruntung mendapat kesempatan belajar teknik ini langsung dari Tom di tahun 2009.
Anna Wise, selama lebih dari 35 tahun, mengukur gelombang otak klien-kliennya, membimbing mereka masuk kondisi meditatif sangat dalam menggunakan mesin EEG Mind Mirror. Saya belajar dengan Anna Wise di tahun 2009.
Selanjutnya saya menggunakan dua mesin EEG ini mengukur gelombang otak para subjek di pelatihan saya, mendapat banyak data penting, korelasi antara kondisi hipnosis, kesadaran, memori, emosi, pola dan komposisi gelombang otak, dan akhirnya sampai pada satu simpulan yang menjadi dasar merumuskan definisi hipnosis.
Saya jelaskan pada sahabat ini, definisi hipnosis versi APA dan AWGI tentu beda dengan definisi yang dinyatakan oleh para pakar hipnosis generasi lama. Tidak ada yang salah dengan masing-masing definisi, karena definisi ini seturut zamannya. Yang kita gunakan, terutama dalam penulisan tesis, tentu adalah definisi terkini.
Saya beri penguatan pada sahabat ini. Saya bilang, suatu saat nanti, bila ia telah benar-benar mencapai level kepakaran mumpuni dan diakui di dunia hipnosis / hipnoterapi, ia boleh dan berhak menetapkan definisinya sendiri. Ia tidak harus ikuti definisi orang lain.
Memang di awal, kita menulis dengan merujuk pada definisi pakar sebelumnya. Biasanya kita akan menulis "Menurut ......, hipnosis adalah.......".
Suatu hari nanti, saya katakan padanya, ia akan menulis artikel dengan kalimat, "Menurut saya........, hipnosis adalah........."
Ini yang saya sangat nantikan. Selama ini kebanyakan orang hanya mengutip dan selalu bilang, "Menurut...........", dan sangat jarang atau hampir tidak pernah saya jumpa tulisan, "Menurut saya.......".
Saya doakan ia bisa segera tuntas melakukan pengumpulan data dan menyelesaikan penulisan tesisnya dan memberi kontribusi positif untuk kemajuan hipnosis dan hipnoterapi di Indonesia.

Gelombang Otak, The Awakened Mind, dan Meditasi
22 Desember 2023Oleh: Dr. Dr. Adi W. Gunawan, ST., MPd., CCH®
Saya pertama kali belajar gelombang otak dan manfaatnya di tahun 1993 saat mengikuti pelatihan The Silva Method, di Surabaya, dengan Pak Lasmono Dyar.
Selama lima hari, dengan bimbingan Beliau, saya belajar masuk ke kondisi alfa optimal, dan menggunakan kondisi ini untuk beragam tujuan.
Ketertarikan belajar dan mendalami, pengukuran, pola, dan makna gelombang otak semakin menguat saat saya belajar hipnosis dan hipnoterapi di tahun 2005. Saya beli banyak buku yang membahas gelombang otak di Amazon.
Di tahun 2005 saya berangkat ke Lugano, Swiss, belajar pengukuran gelombang otak menggunakan mesin EEG Brainwave 1, di The Alpha Learning Institute, dengan Prof. Sean Adam. Ini pelatihan intensif selama empat hari.
Empat tahun kemudian, tahun 2009, saya mendapat kesempatan bertemu, belajar, dan berguru langsung dengan Anna Wise, di Berkeley. Saya belajar tentang gelombang otak, karakteristik setiap gelombang otak, komposisi gelombang otak dan kesadaran, meditasi, dan pengukuran gelombang otak menggunakan mesin EEG Mind Mirror, melalui pelatihan privat dan sangat intensif selama 14 hari.
Di tahun yang sama, saya belajar pengukuran gelombang otak menggunakan mesin EEG DBSA di Camarillo, dengan Tom Silver. Ini pelatihan privat dan intensif selama dua hari tentang pola gelombang otak, kedalaman kondisi hipnosis, hipnoterapi, dan kesadaran.
Di tahun 2010 dan 2013 saya belajar neurofeedbeck di EEG Institute, Woodland Hills, California, total selama 9 hari, dengan Sue dan Sigfried Othmer, dua pakar, peneliti, dan pengajar terbaik di bidang ini.
Menggunakan empat mesin EEG dengan tujuan khusus, saya melakukan pengukuran gelombang otak, melihat pola dan korelasi gelombang otak dan kesadaran, dan selanjutnya menerapkannya dalam menyusun protokol induksi hipnosis Adi W. Gunawan Induction yang diajarkan di kelas Scientific EEG & Clinical Hypnotherapy® (SECH) dan protokol meditasi The Awakened Mind.
Saya sungguh beruntung karena diterima sebagai murid Anna Wise sebelum Beliau berpulang. Beliau menerima saya sebagai murid, setelah melakukan pengecekan gelombang otak saya, khususnya delta.
Saya katakan bahwa saya sangat beruntung karena Anna Wise mengajari saya intisari pengetahuan, temuan, pengalaman, pemahaman dari hasil penelitian dan pengembangan yang ia lakukan selama lebih dari 35 tahun, beserta teknik-teknik luar biasa dalam melatih dan mencapai pola gelombang otak "awakened" atau "terbangun".
Secara sederhana, pengukuran gelombang otak menggunakan dua parameter: frekuensi dan amplitudo. Frekuensi menggunakan angka antara 0,1 hingga 100 dengan satuan Hertz (Hz). Sementara amplitudo (daya) menggunakan angka antara 10 hingga 100, dengan satuan microvolt. Menggunakan Mind Mirror, dapat diukur lima gelombang otak: delta, theta, alfa, beta, dan gamma. Berikut ini uraian ringkas dari tiap gelombang otak.
DELTA
Delta adalah gelombang otak dengan frekuensi paling lambat, pada kisaran 0.1 - 4 Hz. Delta adalah ciri dari tidur yang dalam, tidur tanpa gerakan mata cepat (nonrapid eye movement, NREM).
Amplitudo delta yang sangat tinggi juga ditemukan pada orang-orang yang memiliki koneksi dengan pikiran non-lokal, bahkan saat mereka dalam kondisi sepenuhnya sadar. Otak para meditator dan penyembuh memiliki lebih banyak gelombang delta daripada orang biasa.
Saat individu merasakan emosi, baik positif atau negatif, deltanya menjadi aktif. Intensitas emosi yang dialami individu menentukan tinggi rendahnya amplitudo delta yang aktif pada saat itu.
Delta juga adalah “radar” yang berfungsi mendeteksi, membaca informasi nonverbal, vibrasi, emosi, dan energi. Semakin aktif dan kuat delta, semakin peka individu mendeteksi dan menerima informasi-informasi ini.
Saat meditasi, para meditator menghasilkan delta dengan amplitudo tinggi. Mereka melaporkan pengalaman transenden, menggambarkan merasa satu dengan alam semesta, perasaan harmoni dan kesejahteraan yang luar biasa (Johnson, 2011).
THETA
Frekuensi theta lebih cepat dari delta, pada kisaran 4 - 8 Hz. Theta adalah ciri dari tidur ringan. Ketika kita bermimpi, mata kita bergerak dengan cepat dan otak berada pada frekuensi dominan theta. Theta adalah frekuensi tidur dengan gerakan mata cepat (rapid eye movement, REM).
Theta juga adalah frekuensi dominan dari orang yang sedang dalam kondisi hipnosis, penyembuh, dan orang yang berada dalam keadaan sangat kreatif (Kershaw & Wade, 2012). Theta adalah tempatnya memori. Saat kita mengingat sesuatu, mengakses memori, theta aktif.
Selama proses penyembuhan intens, sering dijumpai amplitudo gelombang theta yang tinggi. Theta telah diidentifikasi sebagai gelombang otak khas selama sesi penyembuhan berbasis energi (Benor, 2004).
Jika seseorang sedang melakukan penyembuhan pada orang lain, gelombang theta yang besar terlebih dahulu muncul pada penyembuh, kemudian pada yang mendapat penyembuhan.
Dalam satu studi, seorang penyembuh dan klien dihubungkan ke EEG. Pemantauan EEG dari penyembuh menunjukkan 14 periode theta yang berkelanjutan pada frekuensi tepat 7.81 Hz. Pemantauan EEG klien menunjukkan ia beralih ke frekuensi yang sama, menunjukkan adanya sinkronisasi antara penyembuh dan yang mendapat penyembuhan (Hendricks, Bengston, & Gunkelman, 2010).
ALFA
Alfa, gelombang otak pada kisaran antara 8 - 12 Hz, adalah keadaan optimal dari kewaspadaan yang rileks. Alfa, berada di tengah rentang frekuensi, membentuk jembatan antara dua frekuensi tinggi, beta dan gamma, dan dua frekuensi rendah, theta dan delta (Cade & Coxhead, 1979).
Alfa menghubungkan dunia luar, pikiran sadar, beta, dan pikiran asosiatif gamma, dengan dunia dalam, pikiran bawah sadar, theta dan delta.
Kekayaan dan kedalaman warna, kejelasan suara, sensasi pada setiap gambaran mental dan pengalaman internal sepenuhnya ditentukan oleh aktivitas dan daya alfa pada saat kita mengalami pengalaman internal.
Sebagian alfa adalah bagian dari pikiran bawah sadar, bersama delta dan theta, dan sebagian lagi termasuk ke dalam pikiran sadar.
Saat kita merasa takut, gelombang alfa menghilang dan mengakibatkan hambatan alfa (alpha blocking). Kita masih punya beta, theta, dan delta. Namun ketiadaan alfa menyebabkan informasi dari theta dan delta tidak bisa naik ke permukaan, beta, pikiran sadar, sehingga tidak diketahui.
BETA
Beta adalah gelombang otak yang terbagi menjadi dua bagian: beta rendah (12-15 Hz) dan beta tinggi (15-40 Hz). Beta inilah yang dikenal sebagai pikiran sadar.
Gelombang beta aktif bila kita berpikir, memberi penilaian atau makna pada sesuatu, mengkritik, membuat daftar, menganalisis, atau berbicara pada diri sendiri (self talk).
Untuk berpikir santai, belajar, dan menyerap informasi, kita butuh beta rendah. Beta rendah adalah frekuensi yang menyinkronkan fungsi otomatis tubuh kita, sehingga juga disebut frekuensi ritme sensorimotor, atau SMR.
Beta tinggi adalah "monkey mind", pikiran yang lompat ke sana ke mari, tidak bisa diam, dan adalah ciri orang cemas, frustasi, atau stres. Beta tinggi inilah yang selalu mengganggu para meditator sehingga sangat sulit fokus karena pikiran terus aktif.
Semakin stres seseorang, semakin aktif beta tinggi dan semakin besar amplitudo beta yang dihasilkan oleh otak mereka. Emosi negatif seperti kemarahan, ketakutan, rasa bersalah, dan malu menghasilkan lonjakan besar beta tinggi dalam pembacaan EEG.
Beta tinggi yang sangat aktif menonaktifkan wilayah otak yang menangani pemikiran rasional, pengambilan keputusan, memori, dan evaluasi objektif (LeDoux, 2002). Aliran darah ke korteks prefrontal, "otak berpikir", berkurang hingga 80 persen. Terkecuali oksigen dan nutrisi, kemampuan otak kita untuk berpikir jernih turun drastis.
GAMMA
Gamma adalah gelombang otak dengan frekuensi paling cepat, pada kisaran 40 - 100 Hz. Gelombang ini muncul terutama saat otak sedang dalam proses pembelajaran, membuat asosiasi antarfenomena, dan mengintegrasi informasi dari berbagai bagian otak.
Otak yang menghasilkan banyak gelombang gamma mencerminkan organisasi saraf yang kompleks dan tingkat kesadaran yang tinggi.
Gelombang gamma terkait dengan tingkat fungsi intelektual yang sangat tinggi, kreativitas, integrasi, puncak pengalaman, dan perasaan "berada dalam zona".
Gelombang gamma mengalir dari bagian depan ke bagian belakang otak sekitar 40 kali per detik (Llinás, 2014). Menurut para peneliti, gelombang osilasi ini menghubungkan aktivitas otak dengan pengalaman subjektif akan kesadaran (Tononi & Koch, 2015).
Dalam satu studi, dilakukan pengukuran gelombang otak para biksu yang melakukan meditasi cinta kasih. Hasil pengukuran dengan mesin EEG menunjukkan lonjakan besar gelombang gamma di otak mereka (Davidson & Lutz, 2008).
Lonjakan gelombang gamma yang diukur pada otak para biksu ini adalah yang terbesar yang pernah tercatat. Para biksu melaporkan bahwa mereka mengalami keadaan sukacita.
The Awakened Mind
Mind Mirror dicipta oleh Maxwell Cade, ilmuwan dan biofisikawan Inggris, di tahun 1976. Ini adalah mesin EEG unik karena memberi gambaran visual yang jelas pola gelombang secara waktu nyata.
Mind Mirror, seperti yang dijelaskan Anna Wise, berbeda dengan elektroensefalografi lain, terutama minat pengembangnya bukan pada keadaan patologis (seperti yang diukur oleh perangkat medis), tetapi pada keadaan optimum yang disebut Awakened Mind.
Alih-alih mengukur gelombang otak subjek bermasalah, pencipta Mind Mirror mencari orang-orang yang paling berkembang dan sadar secara spiritual, yang bisa mereka temukan.
Dengan menggunakan Mind Mirror, selama lebih dari 20 tahun, Maxwell Cade merekam pola gelombang otak lebih dari empat ribu subjek yang menjalani praktik spiritual kuat.
Ia berhasil menemukan dan memetakan pola umum gelombang otak pada subjek yang adalah para swami, meditator, yogi, master Zen, dan penyembuh.
Dari hasil penelitian intensif Maxwell Cade didapat temuan penting yaitu para subjek ini, saat berada di kondisi meditatif yang dalam, memiliki pola gelombang otak yang sama, terlepas teknik yang mereka gunakan. Pola ini disebut dengan pola The Awakened Mind, terdiri dari beta rendah, alfa, theta, dan delta dengan komposisi yang pas.
Keberadaan alfa menjadi jembatan yang menghubungkan pikiran sadar (beta), pikiran bawah sadar (theta) dan pikiran nirsadar (delta).
Dari hasil pengukuran menggunakan Mind Mirror ditemukan orang dengan kecemasan tinggi menghasilkan banyak beta tinggi dan hanya sedikit alfa, theta, dan delta.
Saat orang mulai menjadikan meditasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, mereka mengembangkan amplitudo alpha, theta, dan delta yang lebih tinggi daripada sebelumnya.
Sebuah studi penting memeriksa pola gelombang otak para praktisi meditasi dari lima tradisi kontemplatif yang berbeda, mulai dari qigong hingga Zen. Studi ini membandingkan fungsi otak para meditator dalam kondisi kesadaran normal dan selama meditasi (Lehmann et al., 2012).
Setelah berhasil membangun gambaran lengkap tentang bagaimana seluruh otak berfungsi, para peneliti dalam studi ini menyimpulkan bahwa model paling informatif adalah membandingkan beta dengan delta.
Mereka mengukur rasio beta terhadap delta sebelum, selama, dan setelah meditasi. Meskipun tradisi meditasi menawarkan ajaran yang sangat berbeda, mulai dari membaca kalimat doa, melakukan gerakan tertentu, hingga duduk diam, terdapat kesamaan pada gelombang otak para meditator ini, yaitu terjadi pengurangan beta dan peningkatan delta.
Para peneliti mengidentifikasi “berkurangnya saling ketergantungan fungsional antarwilayah otak secara global,” sebuah perubahan dalam fungsi otak yang menunjukkan terjadi peluruhan pada diri lokal (ego).
Pola otak beta rendah dan delta tinggi mencirikan apa yang disebut sebagai "pengalaman subjektif tidak terlibat, pemisahan diri dan melepaskan, serta kesatuan total dan peleburan batas ego" ketika kesadaran para praktisi meditasi beralih menjadi satu dengan medan universal non-lokal.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa meditasi yang dilakukan secara konsisten, memindahkan otak ke zona fungsional baru yang mencakup lebih banyak delta daripada normal sebelumnya. Otak meditator memproses informasi dengan cara yang sangat berbeda dari otak rata-rata (Dispenza, 2017).
Ketika diri lokal meninggalkan keterikatan dengan tubuh dan menyatu dengan pikiran nonlokal, terjadi lonjakan delta yang besar. Gelombang delta dengan amplitudo tinggi menjadi stabil ketika para meditator mengintegrasikan dua keadaan ini (Pennington, 2017).
Dalam meditasi kita tetap membutuhkan beta, walaupun hanya sedikit saja, untuk bisa mengetahui atau menyadari apa yang sedang kita alami. Bila tidak ada beta maka kita sama sekali tidak akan tahu atau ingat yang terjadi atau alami saat meditasi.
Gelombang Otak, Meditasi Samatha dan Vipassana
Meditasi samatha dilakukan dengan memusatkan perhatian atau konsentrasi pada objek tertentu hingga akhirnya pikiran terkendali, menjadi diam, dan hening. Bila dilihat dari pola gelombang otak, meditasi samatha bertujuan “men-off-kan” gelombang beta, khususnya beta tinggi.
Umumnya meditator menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk belajar mendiamkan pikirannya, namun tidak berhasil. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti bermeditasi karena tidak merasakan manfaat.
Meditator sulit menenangkan pikiran mereka karena tidak melakukan persiapan dengan baik, khususnya pada aspek fisik dan emosi. Biasanya mereka langsung duduk dan fokus pada napas. Ini tidak efektif untuk membuat pikiran diam.
Selain itu, sulitnya meditator mendiamkan pikiran juga disebabkan oleh aktifnya beta tinggi akibat kondisi emosi atau suasana hati yang tidak kondusif, posisi duduk yang tidak tepat membuat otot paha dan tubuh menjadi tegang, sehingga tidak mungkin bisa mencapai kondisi pikiran yang rileks.
Saat seseorang telah mampu “men-off-kan” pikiran sadarnya (beta), pada saat itu ia telah masuk ke kondisi meditatif yang sangat dalam. Meditasi sebenarnya adalah gelombang otak yang terdiri dari beta rendah sesedikit mungkin, banyak alfa, theta, dan atau tanpa delta.
Vipassana adalah meditasi perhatian penuh, instrospeksi, observasi realitas, kewaspadaan objektif, dan belajar dari pengalaman setiap momen. Inti dari meditasi ini adalah mengamati segala proses mental atau fisik yang paling dominan pada saat ini, menyadarinya, mencatat, ingat ketika lenyap, tanpa memberi makna, menghakimi, menilai, memberi label, melibatkan emosi, atau berusaha dengan sesuatu cara mengubah pengalaman ini.
Pengalaman membuktikan bahwa cukup sulit atau bahkan tidak mungkin bisa melakukan pengamatan pada bentuk-bentuk pikiran, perasaan, atau sensasi fisik yang muncul saat pikiran sadar masih sangat aktif. Apalagi jika yang aktif adalah beta tinggi.
Jelas sangat sulit melakukan pengamatan jika piranti yang digunakan untuk melakukan pengamatan atau observasi, yaitu pikiran sadar, masih sangat aktif dan sibuk sendiri.
Yang diamati dalam meditasi vipassana, khususnya pada aspek bentuk-bentuk pikiran dan perasaan yang muncul, sebenarnya berasal dari pikiran bawah sadar dan nirsadar.
Dari pikiran bawah sadar biasanya muncul memori atau ingatan kejadian masa lalu, dan biasanya berisi muatan emosi intens, baik positif maupun negatif.
Saat memori ini muncul, baik dalam bentuk gambar atau rangkaian kejadian, sebenarnya pada saat yang sama, emosi yang berhubungan dengan memori ini juga aktif.
Dengan demikian, adalah sangat penting bagi seorang meditator untuk tidak masuk ke dalam pengalaman itu, karena biasanya mengandung emosi intens, dan cukup hanya mengetahui, menyadari, mencatat, dan mengingatnya ketika lenyap atau hilang.
Kemampuan untuk bisa menjadi pengamat pasif, tidak masuk ke dalam objek yang diamati, hanya bisa dicapai bila pengendalian diri kita baik dan pikiran sadar (beta) tidak terlalu aktif dan tidak memberikan penilaian atau penghakiman.
Saat kita mampu melihat atau hanya menjadi pengamat, kita telah mampu melakukan disosiasi atau menjaga jarak dengan yang diamati, sehingga tidak dipengaruhi emosi yang melekat pada suatu memori.
Saat kita mampu tenang hanya menyadari, mencatat, dan mengingat kejadian atau pengalaman yang muncul, kita akan tahu dan sadar bahwa kita bukanlah pengalaman atau emosi kita.
Pengalaman atau emosi muncul, pudar, dan hilang. Saat kita memberi jarak atau memisahkan diri dari pengalaman atau emosi itu, mereka tidak bisa memengaruhi diri kita.
Kebijaksanaan yang diperoleh dari meditasi vipassana tidak berasal dari beta, tapi dari theta atau pikiran bawah sadar. Kedalamam meditasi ditentukan oleh kedalaman theta yang berhasil kita capai. Theta adalah tempat terjadinya koneksi spiritual paling dalam. Saat seseorang berada dalam theta yang dalam, ia akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan luar biasa.
Pikiran bawah sadar punya proses berpikir sendiri yang terpisah dari pikiran sadar. Saat kita bermeditasi vipassana, saat pikiran sadar tidak terlalu aktif, informasi atau pemahaman yang berasal dari pikiran bawah sadar akan naik, melalui jembatan alfa, ke pikiran sadar (beta), dan kita menyadari atau tahu (ingat) informasi ini.
Yang dilakukan meditator yang bertahun-tahun melakukan meditasi samatha sebenarnya adalah persiapan untuk awakening atau pencerahan. Para meditator ini biasanya, setelah bertahun-tahun berlatih meditasi, berhasil mengembangkan pola gelombang otak Awakened Mind.
Walau meditator telah lama melakukan meditasi samatha, walau ia telah berhasil mencapai pola Awakened Mind, kondisi ini tidak mampu memfasilitasi pencapaian pencerahan.
Hal ini disebabkan meditasi samatha sebenarnya adalah strategi mencapai kondisi kesadaran spesifik. Kondisi kesadaran ini selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan melatih meditasi vipassana, karena vipassana adalah meditasi berdasarkan isi (content-based meditation).
Yang dimaksud dengan isi, selain sensasi fisik yang dirasakan, juga adalah konten dari pikiran bawah sadar dalam bentuk pikiran dan emosi yang muncul, dirasakan, atau dialami pada saat meditasi berlangsung, pada momen sekarang.
Di pelatihan yang saya selenggarakan, untuk membantu peserta masuk kondisi meditatif yang dalam dengan cepat dan mudah, “men-off-kan” beta tinggi, saya menggunakan protokol meditasi khusus.
Mengikuti protokol ini, sebelum melakukan meditasi, saya menyiapkan kondisi fisik, emosi, suasana hati peserta, dan juga lingkungan yang menunjang proses meditasi.
Setelahnya, dengan tuntunan yang sangat sistematis, peserta dibimbing masuk ke kondisi meditatif sangat dalam, pikiran mereka menjadi diam, hening, bening, hati menjadi sangat tenang, damai, bahagia.
Keheningan ini seperti kita, di pagi hari, berada di telaga kecil dengan air yang sangat jernih, tenang, bening, dengan kabut tipis di atas permukaan air yang diam seperti cermin. Tentu suasana batin seperti ini sungguh sangat luar biasa.
Dalam kondisi ini, saat vibrasi kolektif sangat kuat, saya memasang jangkar (anchor) di pikiran bawah sadar peserta. Jangkar ini mereka gunakan untuk masuk kembali ke kondisi meditatif dengan cepat dan mudah, hanya butuh beberapa detik saja.

Progresi Dalam Hipnoterapi
2 November 2023Oleh: Dr. Dr. Adi W. Gunawan, ST., MPd., CCH®
Dalam hipnoterapi terdapat dua strategi, khususnya yang memanfaatkan fenomena mental berkaitan dengan penelusuran garis waktu: regresi (age regression) dan progresi (age progression). Progresi adalah fenomena hipnosis melibatkan mengalami masa depan seakan terjadi di masa sekarang (Torem, 1992; Bonshtein dan Torem 2017). Idealnya, pengalaman ini melibatkan semua indra dan diperkuat dengan emosi (Gunawan, 2008).
Bila regresi bertujuan menemukan akar masalah, kejadian di masa lalu, penyebab simtom yang dialami individu di masa kini, progresi sebaliknya bertujuan mencipta solusi masalah melalui simulasi capaian masa depan.
Strategi ini dapat dilakukan dengan pertama menuntun klien masuk kondisi hipnosis dalam, dilanjutkan dengan simulasi kejadian masa depan, sebagai hasil akhir yang diinginkan.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Watzlawick (1984) bahwa pemikiran dan imajinasi seseorang tentang masa depannya memengaruhi realitas masa depannya.
Sementara menurut Erickson (1954, 1980) teknik-teknik terapi berhubungan dengan progresi dirancang untuk berfungsi mengatasi rasa putus asa tentang masa depan. Erickson menggambarkan progresi sebagai teknik difasilitasi hipnosis yang ia namakan “pseudo-orientation in time” (orientasi semu waktu).
Strategi terapi berbasis progresi digunakan dalam hipnoterapi dengan pemikiran klien menjalani sesi terapi untuk mengubah masa depan, bukan masa lalu.
Salah satu teknik terapi berbasis progresi adalah “Back from the Future” atau “Kembali dari Masa Depan”. Dalam teknik ini, klien, dalam kondisi hipnosis, dituntun menyusuri garis waktu, maju ke masa depan, ke suatu masa dan tempat di mana ia telah berhasil mencapai resolusi masalah yang ia alami.
Selanjutnya, klien disugesti untuk menerima masa depan ini sebagai masa kini, dan terapis bertanya pada klien apa yang telah ia pelajari atau lakukan hingga mampu menyelesaikan masalahnya.
Teknik “Back from the Future” telah banyak digunakan dalam menangani beragam kondisi atau masalah seperti depresi (Torem, 2006, 2017b), gangguan makan (Torem, 1991, 2001, 2017c), kendali terhadap kekerasan yang dilakukan pada diri sendiri (Torem, 1995, 1997), untuk penguatan ego atau peningkatan kepercayaan diri (Torem, 1990), untuk integrasi ego state yang terpisah (Torem dan Gainer, 1995), untuk penanganan mual saat hamil (Torem, 1994), dan penanganan gangguan autoimun (Torem, 2007, 2017c).
Teknik ini juga telah digunakan dengan sangat berhasil dalam bidang olahraga (Stanton, 1994), dan mengatasi rasa sakit kronis (Jensen, 2011, 2017).
Torem (2017) menggunakan varian lain dari teknik berbasis progresi yaitu “forward affect bridge”, modifikasi dari teknik “affect bridge” Watkins. Teknik “forward affect bridge” hanya efektif untuk klien dengan tingkat sugestibilitas tinggi.
Progresi dapat digunakan dalam dua strategi umum. Pertama, ia digunakan sebagai intervensi terapeutik, dan kedua, digunakan untuk menguji manfaat dan hasil kerja klinis saat ini (Yapko, 2019).
Pemanfaatan progresi sebagai intervensi terapeutik berdasar konsep pengharapan seperti yang dijelaskan oleh Kirsch (2001, 2006).
Pemikiran Yapko (2019) sejalan dengan Gunawan (2008) yang merumuskan manfaat progresi untuk pemrograman pikiran bawah sadar, uji keberadaan hambatan mental, uji hasil terapi, pemberdayaan pikiran bawah sadar dengan pemberian informasi atau sumberdaya yang berasal dari masa depan, dan menemukan atau mencipta solusi.
Cara Kerja Progresi
Teknik berbasis progresi bisa bekerja dengan baik dan efektif bila klien berada dalam kondisi hipnosis dalam, khususnya kedalaman profound somnambulism. Dalam kondisi ini, fungsi kritis (conscious logic) pikiran sadar sudah sangat menurun, sementara yang aktif adalah logika pikiran bawah sadar (trance logic).
Di pikiran bawah sadar sejatinya hanya berlaku satu waktu, sekarang. Pikiran bawah sadar tidak mengenal masa lalu dan masa depan.
Dengan demikian, saat klien dituntun “maju” ke masa depan, yang terjadi di pikirannya, ia berpindah dari satu momen memori ke momen memori lain, baik memori yang adalah rekaman kejadian masa lalu maupun memori hasil rekayasa.
Di pikiran bawah sadar sesungguhnya tidak terjadi pergeseran waktu, semua terjadi di masa kini, di pikiran bawah sadar, namun pikiran sadar, seturut sugesti yang diberikan, memaknai sebagai masa depan.

Regresi Dalam Hipnoterapi
6 September 2023Oleh: Dr. Dr. Adi W. Gunawan, ST., MPd., CCH®
Berbagai kondisi emosi dan perilaku tidak kondusif yang dialami individu tidak muncul tiba-tiba. Kondisi ini disebabkan salah satu atau gabungan dari tujuh kemungkinan: menghukum diri sendiri (self-punishment), pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan (unresolved past experience), konflik internal (internal conflict), masalah saat ini yang tidak terselesaikan (unresolved present issue), keuntungan yang tidak disadari (secondary gain), identifikasi, dan penanaman kepercayaan atau imprint (Tebbets, 1987).
Tujuh kemungkinan sumber masalah ini oleh Tebbets dinamakan tujuh psikodinamika simtom. Berdasar temuan kami, para hipnoterapis AWGI, psikodinamika simtom dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: kejadian masa lalu dan kejadian masa sekarang.
Pemahaman ini sangat penting dalam konteks hipnoterapi karena memampukan dan memudahkan hipnoterapis menangani masalah klien melalui proses yang tepat, tajam, ringkas, mudah, dan efektif sehingga dicapai hasil terapi optimal untuk kebaikan dan kesejahteraan klien.
Dalam hipnoterapi terdapat dua strategi utama penanganan masalah: tanpa memproses akar masalah dan memproses akar masalah.
Penanganan tanpa memproses akar masalah mengutamakan penggunaan sugesti. Sementara penanganan dengan memproses akar masalah menggunakan teknik-teknik hipnoanalisis untuk menelisik pikiran bawah sadar (PBS) klien guna mencari, menemukan, dan memproses tuntas akar masalah.
Akar masalah bisa berupa pengalaman traumatik, belief (kepercayaan), baik yang berasal dari pemaknaan sendiri atau yang ditanamkan oleh figur otoritas ke PBS individu, kejadian atau pengalaman masa lalu yang mengakibatkan tercipta Ego Personality dengan fungsi atau tujuan tertentu dalam diri individu, baik yang aktif penuh atau yang dorman menunggu pemicu untuk menjadi aktif.
Pada banyak kasus yang kami temukan, akar masalah bersumber pada kejadian traumatik masa lalu, tersimpan di memori PBS dalam bentuk rekaman kejadian bermuatan emosi negatif intens.
Khusus penanganan kejadian traumatik, dalam dunia hipnoterapi ada dua kubu. Kubu pertama menyatakan bahwa pengungkapan pengalaman traumatik per se bersifat terapeutik. Dengan kata lain, saat memori traumatik berhasil diungkap atau diketahui maka secara otomatis terjadi kesembuhan.
Kubu kedua, dan ini didukung oleh hasil penelitian dan temuan di ruang praktik kami, menyatakan pengungkapan memori traumatik tanpa diikuti resolusi trauma tidak berdampak terapeutik.
Dalam konteks pengungkapan memori traumatik juga terdapat dua kubu. Kubu pertama hanya memproses kejadian tunggal yang diungkap oleh PBS klien, tanpa melakukan validasi apakah ini kejadian paling awal atau bukan. Sementara kubu kedua berupaya, melalui rangkaian regresi, mencari dan menemukan kejadian paling awal.
Definisi dan Jenis Regresi
Dalam kerangka penyelesaian akar masalah, sangat penting menyimak dengan cermat pernyataan Alexander dan French (1946) tentang pengalaman emosional korektif (corrective emotional experience).
Pengalaman emosional korektif adalah pemaparan ulang individu, dalam situasi yang lebih mendukung, pada situasi emosional yang tidak dapat ia hadapi di masa lalu. Hal ini meliputi proses di mana individu meninggalkan pola perilaku lama dan belajar atau belajar ulang pola-pola baru dengan mengalami kembali kebutuhan dan perasaan-perasaan yang belum terselesaikan di masa lalu (Alexander, French, 1946).
Dalam upaya mengatasi masalahnya, individu harus menjalani pengalaman emosional korektif yang sesuai untuk memperbaiki dampak dari pengalaman-pengalaman traumatik sebelumnya.
Untuk klien bisa menjalani pengalaman emosional korektif, ada empat syarat yang harus dipenuhi. Pertama, proses pemaparan ulang harus dilakukan dalam kondisi hipnosis dalam. Kedua, trance logic berhasil diaktifkan. Ketiga, proses belajar ulang dilakukan pada kejadian paling awal dan kejadian-kejadian lanjutan yang mendasari munculnya simtom. Keempat, afek yang lekat pada setiap kejadian diproses tuntas (Gunawan, 2008).
Cara memaparkan klien pada kejadian masa lalu, seperti yang disarankan oleh Alexander dan French, adalah dengan menggunakan teknik regresi.
Regresi adalah fenomena hipnosis di mana subjek memainkan peran dalam pola simulasi untuk memerankan peristiwa masa lalu dalam kerangka masa kini (Kroger, 1963, 2009).
Weitzenhoffer (2000) mendefiniskan regresi sebagai fenomena hipnosis di mana subjek mengalami kembali kejadian masa lalu secara kognisi, emosi, dan perilaku. Sementara Yapko (2009) mendefiniskan regresi sebagai pencerapan yang diintensifkan dalam pemanfaatan pengalaman memori.
Terdapat dua jenis pengalaman regresi, revivifikasi dan hipermnesia, masing-masing dengan proses mental berbeda. Pengalaman emosional korektif hanya bisa terjadi bila klien mengalami revivifikasi, khususnya jenis parsial, dan tidak efektif bila klien hanya mengalami hipermnesia.
Teknik Regresi
Terdapat sangat banyak teknik regresi. Semua teknik ini dikelompokkan menjadi dua, berbasis nonafek dan afek.
Teknik regresi berbasis nonafek antara lain teknik “Buku Kehidupan”, “Layar Komputer”, “Perahu Kehidupan”, “Karpet Ajaib”, “Terowongan Waktu”, “Kalender”, “Bola Kristal”, “Kotak Masalah”, “Ideomotor”, dan masih banyak lagi. Intinya, teknik ini tidak menggunakan afek atau emosi sebagai bahan bakar yang mendorong klien begerak mundur ke masa lalunya.
Teknik regresi berbasis afek atau dikenal dengan jembatan afek (affect bridge) adalah prosedur hipnotik yang digunakan untuk melacak dan menemukan awal mula kejadian penyebab simtom yang dialami individu di masa kini. Jembatan afek didasarkan pada fakta psikologis bahwa emosi atau perasaan dapat mengaktifkan, mengarahkan, atau meningkatkan daya ingat ( Watkins, 1971; Watkins & Barabasz, 2008; Yapko, 2012)
Dalam proses resolusi pengalaman traumatik, sangat penting kesadaran individu dewasa tetap terjaga, aktif dan hadir sebagai pengamat untuk membangun pemahaman baru yang memberi perspektif baru bersifat terapeutik, yang selanjutnya diaplikasikan di kehidupannya saat ini (Lynn dan Kirsch, 2006; Spiegel, 2010).
Data Hasil Regresi
Sangat penting untuk diketahui bahwa penggunaan regresi hipnotik meskipun dapat mengungkap memori kejadian masa lalu, terutama kejadian masa kecil, tidak berarti dan tidak ada jaminan kejadian ini benar-benar terjadi demikian adanya.
Memori tidak bersifat reproduktif, tapi rekonstruktif. Memori perlu dimengerti sebagai sebuah proses perekaman informasi ke PBS berdasar persepsi individu, dapat mengalami modifikasi atau diubah sepanjang hidup individu untuk memenuhi kebutuhan fungsi dinamis tertentu dalam menjalankan hidup keseharian (Kandel, 2007; Squire dan Kandel, 2008).
Memori dapat terpengaruh baik secara sadar atau tanpa disadari karena sifatnya yang lentur (Sheehan (1998, 1995; Loftus, 2017).
Individu bisa mengalami regresi secara spontan sebagai respon terhadap stimulus eksternal yang terhubung dengan pengalaman traumatik di masa kecil. Ia juga bisa mengalami regresi dengan mengikuti tuntunan terapis.
Saat individu mengalami regresi spontan, ke kejadian masa kecilnya, ia mengalami revivifikasi dan adalah anak kecil berusia seturut kejadian yang ia alami.
Ada individu tersangkut di kejadian ini dan berperilaku sebagai anak kecil. Untuk orang awam, kondisi ini tentu sulit dimengerti. Upaya penyembuhan yang dilakukan biasanya tidak efektif karena tidak menyelesaikan masalahnya, yaitu ia tersangkut di masa lalu.
Hipnoterapis berpengalaman dapat dengan mudah mengenali kondisi ini, dan menggunakan kecakapannya, mampu menuntun individu ini keluar dari kondisi hipnosis, kembali ke kondisi kesadaran sebagai orang dewasa di masa kini.

Meditasi: Tak Kenal Maka Tak Sayang
28 Juni 2023Oleh: Dr. Dr. Adi W. Gunawan, ST., MPd., CCH®
Di banyak kesempatan, saya kerap dapat pertanyaan dari para sahabat tentang meditasi. Para sahabat ini ada yang telah rutin praktik meditasi, ada yang masih pemula, dan ada pula yang baru mulai tertarik dengan meditasi, ingin tahu lebih lanjut, namun belum pernah praktik meditasi.
Pertanyaan yang para sahabat ini ajukan antara lain: “Apa itu meditasi?”, “Apakah meditasi sama dengan mengosongkan pikiran?”, “Berapa lama waktu untuk bermeditasi?”, “Kapan waktu yang tepat untuk bermeditasi?”, “Apa manfaat meditasi?”, dan “Bagaimana cara membuat pikiran tenang dan fokus saat bermeditasi?”
Walau telah banyak publikasi tentang meditasi dan pelatihan meditasi juga telah banyak diselenggarakan, masih banyak yang belum memahami benar tentang meditasi, sehingga ragu atau tidak serius praktik dan berlatih meditasi.
Ada pula yang telah mencoba meditasi untuk beberapa saat, namun karena tidak mengerti caranya, akhirnya berhenti karena tidak mendapat manfaat.
Pemahaman Salah
Penghambat utama seseorang belajar, mendalami, dan praktik meditasi adalah pemahaman salah tentang meditasi.
Ada yang berpikir atau percaya meditasi adalah praktik supranatural, menggunakan mantra, makhluk halus, kuasa gelap, sesajen, jimat, laku atau ritual tertentu.
Ada lagi yang percaya meditasi adalah bagian dari gerakan zaman baru, identik dengan doktrin keyakinan atau agama tertentu, yang bila dipraktikkan akan menggoyahkan iman si praktisi meditasi, mengakibatkan dosa.
Sebagian berpikir meditasi berbahaya karena bisa berakibat praktisinya tersangkut, tidak bisa keluar dari kondisi meditasi, menjadi tidak sadar, dan bahkan bisa kerasukan. Pengertian salah lainnya, meditasi adalah mengosongkan pikiran.
Sudah tentu, mereka yang memegang pemahaman salah tidak akan pernah belajar, praktik, dan berlatih meditasi. Akibatnya, mereka tidak beroleh manfaat dari praktik meditasi yang dilakukan secara benar dan rutin.
Pandangan salah ini, bahwa meditasi adalah kegiatan yang tidak baik, bisa berdampak buruk pada diri individu, baik pada aspek fisik, pikiran, emosi, dan spiritual mengakibatkan fungsi proteksi pikiran bawah sadar (PBS) aktif.
Fungsi proteksi PBS ini menjadi aktif dan bekerja melindungi individu dari hal-hal yang ia (PBS) percaya, pikir, rasa, yakin, asumsikan, kira, persepsikan membahayakan keselamatan individu atau berdampak negatif pada kesejahteraan individu.
Selama individu masih memegang pemahaman salah, ia tidak akan pernah bisa bermeditasi dengan baik, tenang, masuk dan mengalami kondisi meditatif yang dalam, hening, dan mencapai hasil yang diharapkan.
PBS akan membuat pikirannya tidak fokus, melakukan sabotase, dan terus menganggu dirinya sehingga tidak akan pernah bisa bermeditasi, walau segala upaya telah dilakukan.
Makna dan Definisi Meditasi
Berdasar catatan terdokumentasi, diketahui praktik meditasi paling awal dilakukan di India sekitar 1500 SM. Namun para sejarawan percaya bahwa meditasi telah dipraktikkan jauh sebelumnya, sejak 3000 SM.
Kata “meditasi” berasal dari bahasa Inggris “meditation”, berakar kata Latin “meditari”, yang artinya (a) merenungkan, (b) berpikir secara mendalam tentang sesuatu, (c) menelaah secara cermat, penuh perhatian, dan mendalam tentang sesuatu hal dalam waktu lama.
Bila ditilik dari akar katanya, meditasi sejatinya adalah aktivitas berpikir yang semua orang bisa lakukan dengan aman dan nyaman. Dan sesuai maknanya, aktivitas berpikir ini bukanlah aktivitas biasa karena melibatkan proses berpikir mendalam, dilakukan secara sadar, untuk tujuan spesifik.
Untuk dapat mengerti dan berdiskusi tentang meditasi, kita perlu menggunakan definisi sahih. Dan tentunya definisi sahih wajib berasal dari pakar atau praktisi berpengalaman yang telah lama menggeluti meditasi.
Meditasi, menurut Y.M. Sri Paññāvaro Mahathera, adalah kegiatan membawa pikiran dengan penuh kesadaran pada satu objek. Sementara menurut Anna Wise, meditasi adalah kondisi kesadaran dengan pola gelombang otak sangat spesifik. Kondisi meditatif ini dicapai dengan teknik sesuai.
Seturut definisi di atas, meditasi tidak berarti kita harus duduk berdiam diri memerhatikan objek tertentu. Benar, ini adalah salah satu cara bermeditasi. Kita luangkan waktu khusus untuk duduk, hening, menyadari dan fokus pada objek meditasi. Dan meditasi juga bisa dilakukan sambil berjalan.
Meditasi bisa dilakukan kapan pun dan di mana pun. Meditasi adalah menyadari, sadar akan yang kita pikir, ucap, rasa, dan lakukan. Intinya adalah kita menyadari.
Cara mudah untuk bermeditasi, seperti yang diajarkan oleh Y.M. Uttamo Mahathera, adalah dengan sering-sering bertanya pada diri sendiri, “Saat ini saya sedang apa?”
Pertanyaan sederhana ini segera membawa pikiran kita, yang semula sibuk memikirkan berbagai hal, kembali ke saat ini, dan menyadari apa yang sedang kita pikir, ucap, atau lakukan. Inilah esensi meditasi, sadar.
Ada dua jenis meditasi: perhatian terfokus pada objek spesifik dan pengamatan terbuka terhadap persepsi yang berlangsung. Uraian lebih mendalam telah saya tulis dalam artikel Meditasi, Mindfulness, Hipnosis, dan Hipnoterapi.
Terdapat empat puluh objek meditasi. Pemilihan objek bergantung karakter individu. Yang paling sering digunakan sebagai objek meditasi adalah napas atau gerakan perut. Ini adalah objek yang paling mudah digunakan karena selalu tersedia dan lekat dengan diri kita.
Meditasi Itu Mudah
Praktik meditasi adalah praktik melatih kesadaran, kesabaran, kepasrahan, mengembangkan kebijaksanaan, hidup di saat ini, dan percaya pada proses yang dijalani. Praktik meditasi tidak bisa dipaksakan atau harus terjadi seturut kemauan praktisi.
Langkah awal sukses bermeditasi adalah memahami sifat dan cara kerja pikiran. Manusia punya dua pikiran, sadar dan bawah sadar, dengan fungsinya masing-masing.
Saat kita bermeditasi, sejatinya yang kita latih adalah fungsi pikiran sadar untuk mengamati, menyadari, fokus pada objek.
Dengan cara tertentu, kita dapat mengakses dan memanfaatkan sumberdaya pikiran bawah sadar untuk mendukung proses meditasi. Dengan demikian, pikiran sadar bisa menjadi cepat tenang, fokus, dan kuat memegang objek.
Sifat pikiran mudah goyah dan tidak tetap, sulit dikendalikan, senang mengembara sesuka hatinya. Pikiran sangat sulit untuk dilihat, amat lembut dan halus, dan bergerak sesuka hatinya.
Pikiran yang tidak terlatih ibarat kuda liar yang selama ini bebas berlari semaunya sendiri. Tentu, saat kuda ini diikat dengan tali dan ditambatkan pada tiang yang kokoh, ia pasti berontak, tidak mau dikekang.
Pada analogi di atas, kuda adalah pikiran, tali adalah kesadaran, dan tiang adalah objek meditasi.
Temuan penelitian yang dilakukan psikolog dari Harvard University, Matthew A. Killingsworth and Daniel T. Gilbert, dipublikasi di jurnal Science, vol. 330, tahun 2010, dengan judul A Wandering Mind Is an Unhappy Mind, memvalidasi sifat pikiran yang suka berkelana:
People spend 46.9 percent of their waking hours thinking about something other than what they’re doing, and this mind-wandering typically makes them unhappy.
(Orang-orang menghabiskan 46,9 persen dari waktu bangun mereka untuk memikirkan sesuatu selain apa yang mereka lakukan, dan pikiran yang mengembara ini membuat mereka tidak bahagia.)
Berangkat dari pengetahuan akan sifat pikiran, saat praktisi mulai berlatih meditasi, bila awalnya pikiran masih liar, bergerak sesuka hatinya, sulit dikendalikan, ia menerima ini sebagai sesuatu yang wajar, tidak berkecil hati, atau merasa gagal.
Dengan tekad kuat dan konsisten berlatih meditasi, cepat atau lambat pikiran pasti akan “lelah”, seperti kuda liar yang awalnya melawan atau berontak saat diikat pada tonggak, akhirnya tenang, jinak, dan patuh.
Sangat banyak praktisi meditasi pemula, baru bermeditasi satu atau dua kali, saat belum mampu menenangkan pikirannya, merasa kecewa dan frustrasi, merasa gagal, memutuskan berhenti dan tidak lagi mau bermeditasi. Ini keputusan terlalu dini dan sangat disayangkan.
Meditasi, sama dengan berbagai keterampilan lain, perlu dibangun secara bertahap, dan tentunya dengan cara yang benar. Ini butuh upaya sadar, waktu, konsistensi, dan komitmen.
Meditasi dilakukan dengan cara salah, sudah tentu tidak memberi hasil. Saya ingat kisah yang diceritakan guru saya, Anna Wise, saat dulu saya belajar dengan Beliau di Berkeley, Amerika.
Beliau pernah membantu, lebih tepatnya mengajari, seorang meditator, yang telah selama dua belas tahun konsisten berlatih meditasi sehari satu jam, tidak pernah putus.
Namun, selama dua belas tahun meditator ini tidak pernah sekali pun bisa masuk kondisi meditatif yang dalam.
Anna Wise melakukan analisis atas kondisinya dan kemudian beri saran. Meditator ini segera melakukan meditasi seturut saran Anna Wise. Hanya dalam waktu beberapa menit dengan sangat mudah pikirannya menjadi tenang, hening, dan ia berhasil masuk kondisi meditatif sangat dalam, kondisi yang ia rindukan selama dua belas tahun.
Dengan mengerti sifat pikiran, praktisi perlu beri dirinya waktu secukupnya untuk bisa berlatih dan menenangkan pikirannya. Ini tidak perlu dikejar atau dipaksakan, karena pasti terjadi dengan sendirinya. Syaratnya, ia konsisten berlatih.
Pikiran yang terkendali membawa kebahagiaan. Orang bijaksana selalu menjaga pikirannya. Orang yang menjaga pikirannya akan berbahagia.
Postur Tubuh Saat Bermeditasi
Sebelum bermeditasi, agar dicapai hasil optimal, praktisi perlu memerhatikan hal-hal berikut.
Praktisi perlu menetapkan tujuan bermeditasi. Penetapan tujuan ini berfungsi sebagai target yang jelas untuk pikiran.
Meditasi butuh waktu dan tidak bisa dilakukan terburu-buru. Sediakan waktu yang cukup, waktu yang benar luang dan tidak terganggu selama minimal tiga puluh hingga enam puluh menit.
Bermeditasilah di ruang atau tempat yang tenang, tidak terganggu, dan matikan semua gawai. Saat anda bermeditasi, ini adalah Me-Time anda. Hargai dan manfaatkan waktu ini dengan sebaiknya.
Usahakan suhu ruang nyaman dan mendukung, jangan terlalu dingin atau panas. Bila kebetulan suhu ruang tempat anda bermeditasi cukup dingin, gunakan baju agak tebal atau selimut agar tubuh hangat dan nyaman.
Berpakaian longgar dan nyaman agar tubuh tidak mengalami hambatan atau gangguan.
Usahakan untuk bermeditasi di tempat dan waktu yang sama setiap hari. Ini bertujuan membangun kebiasaan dan pembiasaan untuk tubuh dan pikiran.
Perhatikan postur tubuh saat bermeditasi. Ada enam posisi duduk bermeditasi: quarter lotus, half lotus, full lotus, Burmese position, Seiza, dan duduk di kursi atau menggunakan bantal.
Bila anda duduk bersila di lantai, apa pun posisi kaki anda, pastikan anda bisa tetap merasa nyaman selama bermeditasi.
Bila anda duduk di kursi, duduklah dengan punggung tegak, tidak bersandar di kursi, dan telapak kaki menapak lantai.
Selanjutnya, perhatikan posisi bahu, kedua lengan, dan kepala. Bahu perlu rileks, nyaman. Letakkan kedua tangan di pangkuan atau di atas paha. Arahkan dagu sedikit ke bawah, dan rahang sedikit membuka.
Setelah semua persiapan ini, mulailah bermeditasi, dan nikmati prosesnya.
Dua Cara Memegang Objek
Ada dua cara yang bisa digunakan praktisi meditasi untuk membuat pikiran terikat pada objek meditasi. Cara pertama, ini yang paling sering dipraktikkan oleh para praktisi meditasi, yaitu berusaha secara sadar mengarahkan pikiran untuk memegang objek meditasi.
Saat pikiran bergerak, bergeser memikirkan hal lain, praktisi sadar akan hal ini dan dengan lembut mengarahkan pikiran kembali pada objek meditasi. Demikian seterusnya, hingga akhirnya pikiran semakin kuat terikat pada objek, dengan durasi semakin panjang.
Ada banyak praktisi meditasi mengalami kesulitan mengarahkan pikiran mereka agar bisa kuat memegang objek. Biasanya yang mereka alami, saat mereka semakin berusaha memfokuskan pikiran, bukannya semakin tenang, pikiran justru semakin aktif memikirkan hal-hal lain.
Cara kedua, dengan teknik tertentu, pikiran dibuat menjadi tenang, diam terlebih dahulu, Setelah kondisi ini tercapai, barulah pikiran diberi objek.
Pada cara kedua, praktisi meditasi akan dituntun masuk ke kondisi pikiran tenang, diam. Kemudian, ia diberi jangkar (anchor) agar dapat kembali ke kondisi ini sendiri.
Selanjutnya, sebelum bermeditasi, ia aktifkan terlebih dahulu jangkarnya, ia masuk ke kondisi pikiran tenang untuk beberapa saat, baru kemudian ia mengarahkan pikiran pada objek meditasinya.
Ada yang suka cara pertama dan ada yang suka cara kedua. Semuanya baik dan berpulang pada masing-masing praktisi. Yang penting tujuan meditasi tercapai.
Manfaat Bermeditasi
Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan bermeditasi. Telah banyak dilakukan penelitian ilmiah untuk mengetahui dampak dan manfaat meditasi terhadap kesehatan fisik dan mental. Hasil berbagai penelitian ini telah dipublikasi di jurnal-jurnal internasional.
Anda bisa membaca hasil penelitian ini dengan cara masuk ke www.Scholar.Google.com dan ketik kata kunci “meditation benefit”, “meditation benefits scientific evidence”, atau “mindfulness meditation benefits”. Nanti akan muncul sangat banyak tautan artikel yang bisa anda akses dan pelajari.
Secara ringkas, praktisi yang rutin berlatih meditasi setiap hari akan beroleh manfaat berikut: pikiran menjadi tenang, lebih fokus, hati damai bahagia, lebih ceria, kualitas tidur meningkat, tubuh lebih berenergi, daya tahan tubuh meningkat, stres berkurang, lebih tahan terhadap stres, lebih kreatif, refleks meningkat, tekanan darah turun.
Secara lebih ringkas lagi, untuk mengerti manfaat meditasi, saya biasa gunakan analogi gelas berisi air dan pasir.
Saat kita aktif menggunakan pikiran, ini sama dengan kita mengaduk gelas berisi pasir. Air di dalam gelas menjadi keruh.
Meditasi sama dengan kita berhenti mengaduk gelas, meletakkan dan mendiamkan gelas dan isinya apa adanya, mengizinkan pasir yang tadinya bertebaran di air, secara perlahan tapi pasti, kembali turun dan mengendap di dasar gelas. Setelahnya, air di gelas menjadi bersih, bening.
Demikian halnya pikiran. Saat pikiran jernih, kita dapat lebih tenang dan objektif dalam melihat dan menyikapi sesuatu. Dan ini berdampak sangat positif untuk diri kita.
Sehari kita butuh bermeditasi minimal selama tiga puluh menit. Untuk mereka yang sangat sibuk, sangat disarankan bermeditasi hanya enam puluh menit. Semakin tinggi kesibukan, semakin kita butuh bermeditasi agar pikiran kembali segar, jernih, dan bisa bekerja optimal untuk kebaikan kita.
Untuk para sahabat yang ingin belajar dan praktik meditasi, saya sangat sarankan agar anda belajar pada guru meditasi berpengalaman dengan rekam jejak yang baik. Ini bertujuan agar anda mendapat bimbingan yang benar sehingga mampu bermeditasi dengan cara yang benar dan beroleh manfaat seperti yang diharapkan.

Konseptualisasi Pikiran Bawah Sadar
9 Mei 2023Oleh: Dr. Dr. Adi W. Gunawan, ST., MPd., CCH®
Konseptualisasi pikiran bawah sadar datang dalam tiga gelombang besar formulasi teoretis. Gelombang pertama adalah identifikasi pikiran bawah sadar oleh Sigmund Freud lebih dari 100 tahun lalu.
Ini adalah teori pertama kepribadian proses ganda (melibatkan pikiran sadar dan bawah sadar) dan mewakili "penemuan" pikiran bawah sadar.
Pentingnya pikiran bawah sadar lebih lanjut ditekankan ketika Freud berhipotesis bahwa banyak pengalaman dan perilaku manusia sebenarnya adalah hasil/akibat pengaruh pikiran bawah sadar daripada proses pikiran sadar.
Menurut Freud, pikiran bawah sadar lebih primitif dan beroperasi sesuai dengan proses berpikir primer, dengan ciri dan mekanisme utama berupa fantasi, pemenuhan keinginan, pemindahan, kondensasi, representasi simbolik, dan asosiasi (Epstein, 1994). Sebaliknya, pikiran sadar bekerja menggunakan proses berpikir sekunder, yaitu aturan logika dan rasionalitas.
Konsep pemrosesan ganda informasi di luar kesadaran, seperti yang diajukan Freud, diterima secara luas. Namun, deskripsi Freud tentang pikiran bawah sadar sebagai sumber motivasi telah dipertanyakan karena dinilai kurang komprehensif.
Gelombang kedua pemahaman tentang pikiran bawah sadar dikembangkan dari perspektif kognitif, bukan psikoanalitik (Epstein, 1994). Dari perspektif ini, pikiran bawah sadar dikonseptualisasikan sebagai ketidaksadaran kognitif dan tidak terkait dengan psikoanalisis.
Sebaliknya, model kognisi bawah sadar ini menyatakan bahwa informasi diproses secara otomatis tanpa upaya sadar dan di luar kesadaran, sebagai mode operasi alami. Kihlstrom (1990) menggambarkan konseptualisasi pikiran bawah sadar ini sebagai ketidaksadaran yang “lebih baik dan lembut” dibandingkan dengan konseptualisasi psikoanalitik.
Keterbatasan konsep ketidaksadaran kognitif adalah bahwa ia tidak mampu menjelaskan dengan baik persepsi dan perilaku yang didorong oleh emosi. Meskipun konsep ini dengan benar mengidentifikasi bahwa kognisi terjadi di luar kesadaran, ia gagal menjelaskan sepenuhnya bagaimana pikiran bawah sadar beroperasi atau memproses informasi. Oleh karena itu, berkenaan dengan hipnoterapi, konsep ketidaksadaran kognitif belum sepenuhnya memuaskan.
Gelombang ketiga pemahaman tentang pikiran bawah sadar terjadi saat Epstein (CEST; Epstein, 1973; 1994; 2003) mengajukan teori kepribadian Cognitive-Experiential Self Theory.
Dalam formulasi teoretis yang diajukan Epstein (1973) dinyatakan bahwa manusia memiliki dua sistem pikiran: sistem rasional dan sistem pengalaman.
Sistem Rasional
Sistem rasional aktif bekerja karena upaya sadar, disengaja, penuh usaha, lebih lambat, logis dan beroperasi terutama melalui penggunaan bahasa. Karenanya, individu paling sadar akan sistem rasional saat dalam kondisi sadar normal (bangun).
Sistem rasional juga berusaha menemukan hubungan sebab-akibat pada sebagian besar rangsangan yang ditemui dalam situasi sehari-hari (Epstein, 2003, 2008, 2014).
Sistem rasional/sadar bertindak sesuai dengan seperangkat prinsip analitis dan dipengaruhi oleh nalar dan logika. Ia beroperasi sejalan dengan pemahaman seseorang tentang aturan penalaran dan bukti, serta gagasan yang dapat ditransmisikan secara budaya. Tindakannya sadar, analitis, penuh usaha, relatif lambat, bebas pengaruh, dan sangat menuntut sumber daya kognitif.
Sistem rasional menyandikan memori melalui semantik atau bahasa, simbol abstrak, angka, huruf, dan kata-kata. Melalui sistem inilah orang dapat memecahkan masalah (rumit) secara efektif, efisien, dan mengambil prinsip-prinsip yang dipelajari dan menerapkannya di seluruh konteks.
Sistem Pengalaman
CEST memperkenalkan pemahaman baru dan lebih komprehensif tentang pikiran bawah sadar. Teori ini secara unik mengidentifikasi pikiran bawah sadar beroperasi sebagai sistem pengalaman yang dipengaruhi oleh emosi dan memproses informasi secara otomatis, cepat, dan mudah.
Menurut teori ini, peristiwa-peristiwa terutama diwakili secara konkret dan imajinatif (Epstein, 1994), dan melalui penggunaan pemikiran, metafora, narasi, skrip, prototipe, dan gambar, sistem pengalaman / bawah sadar melakukan generalisasi dan merespon informasi.
Sistem pengalaman bekerja dengan dorongan emosi dan beradaptasi berdasar pengalaman daripada dengan logika (Epstein, 2008).
Sistem ini telah berkembang selama jutaan tahun, dan telah digunakan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial dan tuntutan situasi yang berubah dari waktu ke waktu.
Sistem ini beroperasi sebagai sistem kognitif yang sangat dipengaruhi oleh emosi dan juga sangat memengaruhi emosi individu. Ia juga meregulasi perilaku, menjadikan pemenuhan rasa senang sebagai tujuan utama dan menghindari rasa sakit, baik secara fisik maupun emosi.
Sistem ini bertindak cepat, berdasar pengalaman, dan tidak disadari, bersifat holistik, asosiatif, dan didorong oleh emosi (Epstein, 1994).
Sistem ini dapat dengan cepat membuat koneksi, terutama jika asosiasi langsung bersifat menyenangkan. Ia lebih lambat berubah karena asosiasi otomatis ini berkembang secara bertahap melalui paparan berulang, atau secara akut melalui pengalaman emosional intens. Ia menyandikan informasi dengan ingatan, gambar konkret, metafora, atau narasi dengan cepat dan sering dihubungkan dengan proses bercirikan getaran, intuisi, naluri, atau firasat (Epstein, 2003, 2013).
CEST menyatakan sistem pengalaman memengaruhi perilaku dan pemikiran individu sehari-hari hampir secara tidak sadar. Melalui sistem ini, individu mengembangkan dan memelihara skema tentang dunia, diri, dan orang lain (Epstein, 2003).
Meskipun sistem rasional mungkin membantu mempertahankan atau membenarkan skema ini, sistem pengalamanlah yang bertanggung jawab atas penerapan otomatis dan penyesuaian skema di seluruh konteks. Sistem pengalaman kurang terorganisir daripada sistem rasional karena terdapat banyak jalur pemrosesan informasi yang dibedakan oleh kondisi afeksi diskrit. Ia juga juga dapat dikelola dengan menyelaraskan pola pemikiran dan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem pengalaman berperan besar dalam mendorong kepercayaan terhadap takhayul, munculnya ketakutan irasional, teori konspirasi, dll. (Epstein, 2014).
Semua informasi diproses oleh dua sistem independen namun saling berinteraksi. Walau sistem rasional (pikiran sadar) dan sistem pengalaman (pikiran bawah sadar) berinteraksi secara sinergis, kedua sistem ini sangat berbeda dalam sifat dan cara kerjanya.
Pengaruh Sistem Pengalaman terhadap Sistem Rasional
Sistem pengalaman bersifat prasadar dan bereaksi cepat terhadap situasi, yang kemudian diikuti oleh sistem pemrosesan rasional.
Karena sistem pengalaman bereaksi secara otomatis dan dipengaruhi oleh emosi, sistem pemrosesan rasional individu dapat mengalami bias akibat respons emosional individu. Proses individu berusaha memahami sistem pemrosesan bawah sadar menggunakan sistem pemrosesan sadar disebut rasionalisasi (Epstein, 2003).
Sistem pengalaman memproses informasi secara holistik untuk tujuan generalisasi dan beroperasi pada level yang berbeda, tinggi dan rendah. Tingkat operasi yang lebih rendah melalui pengkondisian klasik, sedangkan tingkat operasi yang lebih tinggi dari sistem pengalaman adalah pemrosesan heuristik. Pemrosesan heuristik dalam sistem pengalaman memerlukan penalaran asosiatif yang lebih mendasar dibandingkan dengan penalaran kausal yang lebih kompleks secara atribusi seperti sistem rasional. Pengolahan heuristik pengalaman telah ditemukan, meskipun tidak selalu, menjadi sumber irasionalitas (Epstein, 2003).
Pengaruh Sistem Rasional terhadap Sistem Pengalaman
Karena sistem rasional beroperasi pada kecepatan yang lebih lambat daripada sistem pengalaman, ia berada pada posisi yang memungkinkan untuk bisa mengoreksi banyak proses yang dilakukan sistem pengalaman (Epstein, 2003).
Sistem rasional tidak hanya dapat memahami cara kerja sistem pengalaman tetapi juga dapat memahami skema yang mendasarinya. Pemrosesan rasional seperti ini dapat mencakup aspek kesadaran diri dan pengendalian diri, di mana pemikiran analitis memungkinkan seseorang mengesampingkan dorongan atau impuls dan membuat keputusan berbeda. Melalui kejadian berulang seperti ini, pemikiran dan perilaku rasional dapat menjadi kebiasaan atau prosedural.
Cara lain yang memungkinkan sistem rasional dapat memengaruhi sistem pengalaman adalah dengan mengidentifikasi dan memahami aspek sistem pengalaman yang tidak logis dan melakukan tindakan korektif untuk menyesuaikan dan mendorong hasil yang lebih baik. Jenis proses seperti ini dapat lebih mudah dilihat saat menguji penerapan CEST dalam konteks terapi.
Meskipun sistem pengalaman tidak dapat memahami sistem rasional, sistem rasional dapat memahami proses sistem pengalaman. Dengan demikian, pikiran, emosi, dan perilaku maladaptif dapat diperbaiki melalui terapi.
Menurut CEST, terdapat tiga cara menghasilkan perubahan dalam pemrosesan informasi sistem pengalaman.
Pertama, individu dapat dibuat sadar akan pemrosesan pengalaman mereka, dengan cara yang memungkinkan mereka mengakui asal mula irasionalitas dan terlibat dalam pemikiran dan perilaku korektif. Ini kemudian membuka jalan untuk mengubah dan melatih sistem pengalaman sesuai yang diinginkan.
Kedua, pengalaman koreksi diri dapat menyebabkan perubahan dalam sistem pengalaman. Ini dapat berasal dari pengalaman negatif yang dialami atau belajar dari pengalaman secara lebih umum.
Dalam hal ini, idenya adalah bahwa sistem pengalaman akan menghindari emosi negatif, rasa tidak nyaman, dan mengejar emosi positif (selama pengalaman tersebut dapat diterima dan sehat).
Ketiga, perubahan dalam sistem pengalaman kemungkinan besar terjadi ketika individu berusaha belajar melalui narasi, gambaran mental, atau fantasi. Semua cara ini sejalan dengan sistem pengalaman dan dengan demikian memberikan fenomena seperti berbicara dalam bahasa yang sama (Epstein, 2003).
Berikut ini perbandingan kedua sistem, seperti yang dikemukakan Epstein (dalam Weiner, 2013):
Sistem Rasional (Pikiran Sadar)
1. Analitis
2. Logis: Berorientasi pada alasan dan akurasi, beroperasi dengan prinsip realitas.
3. Hubungan sebab-akibat.
4. Lebih berorientasi pada proses.
5. Perilaku dimediasi oleh penilaian kejadian secara sadar.
6. Mengkodekan realitas dalam simbol, kata, dan angka abstrak.
7. Pemrosesan lebih lambat: Mampu melakukan tindakan yang tertunda lama.
8. Berubah lebih cepat: Bisa berubah seturut kecepatan berpikir.
9. Diferensiasi lebih tinggi: Pemikiran yang berdimensi dan bernuansa.
10. Lebih terintegrasi: Terorganisir menurut generalisasi lintas situasi.
11. Berpengalaman secara aktif dan sadar: Individu percaya bahwa ia mengendalikan pikiran sadarnya.
12. Membutuhkan pembenaran melalui logika atau bukti.
Sistem Pengalaman (Pikiran Bawah Sadar):
1. Holistik
2. Emosional: Berorientasi rasa senang-sakit, beroperasi dengan prinsip hedonis.
3. Hubungan asosiatif.
4. Lebih berorientasi pada hasil.
5. Perilaku yang dimediasi oleh “getaran” dan emosi dari pengalaman masa lalu.
6. Menyandikan realitas dalam gambaran konkret, generalisasi primer, metafora, dan narasi.
7. Pemrosesan lebih cepat: Berorientasi pada tindakan segera.
8. Lebih lambat berubah: Perubahan dengan pengalaman berulang atau intens.
9. Diferensiasi lebih kasar: Gradien generalisasi luas; berpikir kategoris.
10. Terintegrasi lebih kasar: Disosiatif, terorganisir dalam bagian oleh kompleks emosional (modul kognitif-afektif).
11. Dialami secara pasif dan prasadar: Kita merasa dikuasai oleh emosi kita.
12. Yakin dengan sendirinya: “Mengalami adalah percaya”

Definisi Hipnosis dan Hipnoterapi Terkini
18 Februari 2023Oleh: Dr. Dr. Adi W. Gunawan, ST., MPd., CCH®
American Psychological Association (APA) Divisi 30, Society of Psychological Hypnosis, telah tiga kali merumuskan definisi hipnosis, tahun 1993, 2003, dan terakhir 2014, sebagai acuan para praktisi dan peneliti pengguna hipnosis dalam kegiatan mereka.
Definisi hipnosis yang dirumuskan APA, tahun 1993, menggambarkan posisi sejumlah peneliti yang mendukung perbedaan perspektif teoretis namun terutama mengidentifikasi hipnosis sebagai prosedur di mana seorang penyembuh profesional atau peneliti memberi sugesti pada klien atau pasien, atau subjek penelitian untuk mengalami perubahan sensasi, persepsi, pikiran atau perilaku (Kirsch, 1994b, p.143).
Definisi ini juga meliputi daftar beberapa kegunaan hipnosis dan menyatakan hipnosis telah digunakan dalam penanganan rasa sakit, depresi, kecemasan, stres, gangguan kebiasaan, dan banyak masalah psikologis dan medis lainnya (Kirsch, 1994b, p.143).
Setelah publikasi definisi resmi hipnosis pada tahun 1994, muncul keprihatinan dan kritik karena definisi ini tidak memuaskan banyak pihak. Definisi ini mendapat kritik karena terlalu panjang dan memiliki keterbatasan teoretis signifikan.
Segera setelah publikasi definisi hipnosis pada tahun 1994, komite eksekutif APA Divisi 30 mulai menangani masalah ini. Namun upaya revisi ternyata menjadi tugas yang tidak mudah. Walau definisi tahun 1994 ini belum memuaskan, ia berlaku selama lebih dari satu dekade.
Kesulitan dari perumusan definisi disebabkan oleh dua faktor. Pertama, mekanisme yang menjadi dasar terjadinya efek hipnosis belum sepenuhnya teridentifikasi. Kondisi ini mengakibatkan sulit tercapai konsensus atas definisi hipnosis. Kedua, alasan timbul ketidaksetujuan atas definisi hipnosis karena argumentasi tentang akurasi suatu definisi pasti terjadi bila definisi ini melibatkan bias teoretis (Elkins dkk, 2015).
Teori-teori hipnosis yang dimaksud antara lain teori neodisosiasi (Hilgard, 1973), teori sosiokognitif (Spanos, 1991), teori pengharapan respon (Kirsch, 1985), dan teori kendali terdisosiasi (Woody dan Bower, 1994).
Setelah melalui proses yang cukup panjang, di tahun 2003, APA Divisi 30 mengumumkan definisi hipnosis, yang dibatasi pada prosedur yang digunakan dalam penelitian dan praktik klinis (Green et al., 2005, p.262).
Definisi hipnosis ini panjangnya dua paragraf:
Hipnosis biasanya melibatkan pengenalan prosedur di mana subjek diberitahu tentang pemberian sugesti untuk pengalaman imajinatif. Induksi hipnotik adalah kelanjutan dari sugesti awal untuk menggunakan imajinasi seseorang, dan dapat berisi penjelasan lebih lanjut dari penjelasan awal. Prosedur hipnosis digunakan untuk mendorong dan menilai respons terhadap sugesti. Saat menggunakan hipnosis, satu orang (subjek) dituntun oleh orang lain (hipnotis) untuk merespon sugesti perubahan pada pengalaman subjektif, perubahan persepsi, sensasi, emosi, pemikiran, atau perilaku. Orang juga dapat belajar swahipnosis, yaitu tindakan melakukan prosedur hipnosis pada diri sendiri. Jika subjek merespon sugesti hipnotik, umumnya disimpulkan telah terjadi hipnosis. Banyak yang percaya bahwa respons dan pengalaman hipnotik adalah karakteristik kondisi hipnosis. Beberapa orang berpikir bahwa tidak perlu menggunakan kata hipnosis sebagai bagian dari induksi hipnotik, sementara yang lain memandang ini sebagai hal penting.
Rincian prosedur dan sugesti hipnotik akan berbeda bergantung pada tujuan praktisi dan tujuan upaya klinis atau penelitian. Secara tradisional, prosedur hipnosis melibatkan sugesti untuk menjadi rileks, meskipun rileksasi bukan keharusan untuk hipnosis, dan berbagai macam sugesti dapat digunakan termasuk sugesti untuk menjadi lebih waspada. Sugesti yang memungkinkan sejauh mana hipnosis dinilai dengan membandingkan respons terhadap skala standar dapat digunakan baik dalam ranah klinis maupun penelitian. Sementara mayoritas individu responsif terhadap setidaknya beberapa sugesti, skor pada skala standar berkisar dari tinggi hingga dapat diabaikan. Secara tradisional, skor dikelompokkan ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Seperti halnya dengan ukuran konstruk psikologis skala positif lainnya seperti perhatian dan kesadaran, arti penting bukti untuk mencapai kondisi hipnosis meningkat seturut skor individu. (Green dkk., 2005, p.262-2633).
Definisi hipnosis tahun 2003 telah mengalami kemajuan berarti, namun kurangnya kehati-hatian dan pembatasan pada prosedur dipandang sebagai kekurangan signifikan.
Di tahun 2013, Dr. Arreed Barabasz selaku presiden Divisi 30 APA menunjuk komite baru, Hypnosis Definition Committee (HDC) untuk merevisi definisi hipnosis. HDC beranggotakan Gary R. Elkins (Ketua), David Spiegel, James R. Council, dan Arreed F. Barabasz.
Untuk mencapai tujuan ini, HDC mengacu pada pedoman berikut:
• Definisi harus berupa deskripsi singkat yang mengidentifikasi objek yang dimaksud dan karakteristiknya.
• Definisi harus bersifat heuristik dan mengakomodir teori-teori alternatif terkait mekanisme hipnosis.
Setelah mendapat banyak saran dan masukan dari berbagai pihak, akhirnya pada tanggal 24 Maret 2014 HDC (APA Divisi 30) berhasil merumuskan dan mencapai konsensus definisi hipnosis yang baru:
"Hipnosis adalah kondisi kesadaran melibatkan perhatian terfokus dan berkurangnya kesadaran periferal yang bercirikan peningkatan kapasitas respons terhadap sugesti (Elkins dkk, 2015, p.6).
Dan definisi hipnoterapi (atau hipnosis klinis) adalah pemanfaatan hipnosis dalam penanganan masalah medis atau psikologis (p.7).
Kami (AWGI) mendefinisikan hipnosis sebagai kondisi kesadaran bercirikan pikiran sadar rileks, fungsi kritis analitis pikiran sadar menurun, disertai meningkatnya fokus dan konsentrasi, sehingga individu menjadi sangat responsif terhadap pesan atau informasi yang diberikan kepada pikiran bawah sadar (Gunawan, 2017).
Definisi hipnosis versi AWGI dan APA Divisi 30 sama-sama menyatakan bahwa hipnosis adalah kondisi kesadaran, karena memang demikianlah adanya, sesuai dengan yang kami temukan dan alami di ruang praktik saat menangani klien.
Sementara definisi hipnoterapi, menurut AWGI, adalah terapi, menggunakan teknik atau metode apa saja, yang dilakukan di dalam kondisi hipnosis, untuk mencapai tujuan terapeutik (Gunawan, 2017).

Fenomena Pull Effect
3 November 2022Oleh: Dr. Dr. Adi W. Gunawan, ST., MPd., CCH®
Beberapa waktu lalu saya menulis tentang fenomena Dapikin. Dalam kesempatan ini, saya akan bahas fenomena menarik lainnya, fenomena Pull Effect.
Pull Effect adalah istilah yang saya ciptakan untuk menjelaskan fenomena unik yang ditemukan dalam proses hipnoterapi.
Ceritanya begini. Dalam proses terapi, seturut protokol AWGI, hipnoterapis melakukan hipnoanalisis, menelusuri labirin pikiran bawah sadar (PBS) klien, tentu atas izin klien, untuk menemukan akar masalah atau kejadian paling awal penyebab simtom.
Dalam beberapa kasus yang kami tangani, dan ini juga terjadi di salah satu sesi live therapy yang saya lakukan minggu lalu di kelas SECH, PBS tidak mengizinkan klien diregresi ke masa lalunya. Yang terjadi adalah PBS menghentikan proses regresi di satu kejadian tertentu, yang kami tahu tidak mungkin adalah akar dari masalah klien.
Klien yang saya terapi punya masalah mudah marah. Emosinya mudah terpicu bahkan untuk hal-hal sepele. Klien sadar ia tidak perlu marah. Namun, saat ada kejadian pemicu, emosi marah klien muncul dan sangat sulit dikendalikan.
Usia klien 35 tahun. Dari pengalaman kami selama ini, biasanya akar masalah terjadi terutama dalam rentang usia antara 0 hingga 10 tahun. Ada ditemukan akar masalah terjadi di usia remaja.
Hasil hipnoanalisis membawa klien mundur ke masa enam bulan lalu, saat ia mengalami kejadian yang membuatnya sangat marah, emosinya benar-benar intens.
Dari hasil verifikasi, diketahui bahwa sumber emosi marah ini bukan di kejadian ini, tapi ada di kejadian pada waktu yang lebih awal lagi.
Saya kembali menggunakan teknik penelusuran PBS untuk menemukan kejadian paling awal. Dua kali upaya penelusuran dilakukan, dua kali PBS memblok dan tidak mengizinkan klien mundur ke masa lalunya.
Apa yang perlu dilakukan dalam situasi ini? Seturut protokol AWGI, hambatan penelusuran ini terjadi dalam dua bentuk. Dan berdasar jenis hambatan yang dilakukan PBS, terapis memutuskan apakah akan tetap mengupayakan regresi lagi atau cukup berhenti sampai di kejadian yang diungkap PBS.
Saya memutuskan untuk berhenti melakukan penelusuran lanjutan, karena kriteria dan jenis hambatan yang dilakukan PBS mengindikasikan kejadian ini, walau baru berselang enam bulan dari saat klien menjalani sesi hipnoterapi, adalah kejadian yang dapat menghasilkan Pull Effect atau Efek Tarikan.
Saya proses kejadian ini hingga tuntas dengan teknik rekonstruksi dan atau rekonsiliasi yang sesuai, tentu menggunakan protokol Dual-Layer Therapy seperti yang diajarkan di kelas SECH.
Hasilnya? Saat dilakukan dua kali pengujian hasil terapi, klien tidak lagi reaktif, atau mudah terpicu emosinya saat mengalami kejadian yang sebelumnya mudah membuat ia marah.
Pertanyaannya, mengapa hanya dengan memproses kejadian yang terjadi dalam waktu dekat, bukan kejadian di masa lalu yang jauh, masalah klien berhasil diatasi?
Kasus terapi lain dilakukan peserta SECH, dalam proses sertifikasi hipnoterapis di AWGI, juga menunjukkan dampak dari Pull Effect.
Peserta ini membantu klien dengan masalah tidak percaya diri bila tampil di depan umum. Saat sesi wawancara, klien cerita bahwa ia merasa marah pada ayahnya. Mestinya, terapis fokus pada masalah utama yang klien sampaikan di Intake Form, tidak percaya diri.
Peserta ini, karena sedang dalam proses belajar, menerapi klien untuk masalah kemarahan pada ayah, bukan tidak percaya diri.
Hasilnya? Kemarahan pada ayah berhasil diatasi, dan bonusnya, rasa tidak percaya diri tampil di depan umum juga turut teratasi. Padahal, terapis tidak secara khusus memproses masalah tidak percaya diri klien.
Pertanyaannya, mengapa walau terapis salah memproses masalah klien, masalah A tapi yang diproses B, masalah A turut terselesaikan? Inilah dampak dari Pull Effect.
Hipotesis saya, Pull Effect hanya terjadi bila klien memenuhi beberapa syarat: klien siap dan bersedia diterapi atas kesadarannya sendiri, klien mendapat edukasi mendalam dan mengerti dinamika kerja PBS, terapis matang menyiapkan PBS untuk proses yang akan klien jalani, kejadian bermuatan emosi negatif intens dan tuntas diproses, dan terapi dilakukan dalam kondisi hipnosis dalam.
Saya katakan hipotesis karena untuk pembuktiannya perlu eksplorasi lebih lanjut. Walau kami sangat ingin tahu lebih jauh tentang Pull Effect, seturut kode etik AWGI / AHKI kami dilarang secara sengaja bereksperimen dengan klien.
Klien datang untuk dibantu mengatasi masalahnya, bukan sebagai subjek eksperimen, walau dampak terapeutik positif bisa dicapai.
Harapan saya, di masa depan, akan ada hipnoterapis AWGI yang melakukan penelitian mendalam tentang Pull Effect dan menuliskannya sebagai disertasi.
Walau Pull Effect berdampak terapeutik positif, kami tidak boleh sengaja melakukannya, karena ini tidak seturut protokol AWGI.
Demikianlah adanya...
Demikianlah kenyataannya...

Hipnoanalisis dan Hipnoterapi Dinamis
16 Agustus 2022Oleh: Dr. Dr. Adi W. Gunawan, ST., MPd., CCH®
Perkembangan dan kemajuan hipnoterapi berjalan seiring berkembangnya praktik, pengetahuan, dan penelitian di bidang hipnoterapi. Sebelum tahun 1960 dikenal tiga pendekatan dalam hipnoterapi: (1) pendekatan simtomatik, fokus pada simtom atau kebiasan, (2) pendekatan suportif, fokus pada relaksasi dan meningkatkan rasa percaya diri klien, dan (3) hipnoterapi dinamis dan atau hipnoanalisis (Breuer dan Freud, 1893-1895/1955; Wolberg, 1945; Watkins, 1949; Gill dan Brenman, 1959; Freytag, 1965; Klemperer, 1965).
Hipnoterapi pendekatan simtomatik dan pendekatan suportif keduanya menggunakan sugesti sebagai sarana utama dalam mencapai tujuan terapeutik. Sementara hipnoterapi dinamis atau hipnoanalisis menggunakan teknik pengungkapan informasi pikiran bawah sadar sebagai sarana resolusi masalah.
Hipnoterapi dinamis sejatinya berbeda dengan hipnoanalisis, walau keduanya menggunakan metode yang sama dalam mengungkap akar masalah (Brown dan Fromm, 1986). Hipnoterapi dinamis berdurasi lebih singkat dibanding hipnoanalisis (Fromm, 1987).
Perbedaan hipnoterapi dinamis dan hipnoanalisis terletak pada jumlah sesi perlakuan dan cara terapis menangani transferen. Dalam hipnoterapi dinamis, jumlah sesi perlakuan berkisar antara lima hingga dua puluh sesi, sementara dalam hipnoanalisis berkisar antara beberapa bulan hingga satu setengah tahun. Ada literatur yang menyatakan durasi lebih lama.
Tujuan hipnoanalisis adalah reorganisasi total kepribadian, sementara tujuan hipnoterapi dinamis adalah sebatas mengatasi masalah yang dialami individu yang berhubungan dengan emosi dan perilaku.
Hipnoterapi yang dipraktikkan oleh para hipnoterapis Adi W. Gunawan Institute of Mind Technology (AWGI) adalah hipnoterapi dinamis dengan fokus perlakuan berkisar antara satu hingga empat sesi. Masing-masing sesi berdurasi antara tiga hingga empat jam.
Berbeda dengan definisi yang ada di literatur, AWGI mendefinisikan hipnoanalisis sebagai strategi mengungkap memori dan emosi kejadian paling awal, akar masalah dan dasar tercipta simtom, yang berhubungan dengan emosi atau perilaku tertentu, dilakukan dalam kondisi hipnosis dalam, dengan sarana eksplorasi vertikal dan horizontal.
Di tahun 1965 Hartland, hipnoterapis Inggris, menggagas teknik penguatan ego, bertujuan meningkatkan kekuatan diri dan kemampuan koping.
Sejak tahun 1981, bertambah dua pendekatan dalam praktik hipnoterapi, pendekatan defisit perkembangan (Baker, 1981; Brown, 1985; Brown dan Fromm, 1986, Copeland, 1986) dan pendekatan behavioral medicine (Brown dan Fromm, 1986).
Hipnoterapi dinamis dan hipnoterapi perkembangan adalah bagian dari hipnoanalisis. Sementara pendekatan simtomatik dan suportif, hipnoterapi perilaku, dan behavioral medicine bukan bagian dari hipnoanalisis.
Teknik-tekik hipnoanalitik adalah prosedur rumit, dipraktikkan dalam modalitas hipnotik dengan tujuan rekonstruksi pikiran bawah sadar klien pada tataran lebih dalam dan mendasar.
Aplikasi teknik hipnoanalitik bertujuan meringankan atau menghilangkan simtom melalui restrukturisasi kognisi dan emosi, akibat konflik intrapsikis, bukan sekadar pemanfaatan sugesti untuk manipulasi simtom.
Dalam praktik aktual, pemanfaatan sugesti, khususnya bila diterapkan seturut pemahaman psikodinamika, dapat dikategorikan sebagai bagian dari strategi penanganan hipnoanalitik. Terapi menjadi hipnoanalitik saat aspek sugesti hanya sebagai pelengkap tujuan utama mencapai pemahaman rekonstruktif.
Dalam hampir semua kasus, simtom klien berhubungan dengan memori dan afek terepresi yang tidak diketahui asal mula kejadiannya. Dalam situasi ini, terapis tidak dapat meregresi klien ke kejadian yang diperkirakan sebagai kejadian paling awal, dan perlu menggunakan strategi regresi lain seturut kondisi dan situasi yang dihadapi.
Strategi yang umum digunakan dalam hipnoanalisis untuk mengungkap akar masalah adalah strategi hipnoprojektif, mengandalkan gambar mental dan visualisasi, dan strategi berdasar ekspresi motor.
Beberapa teknik dalam hipnoprojektif antara lain teknik awan, teknik menatap cermin atau bola kristal, teknik anagram, teknik teater, teknik televisi, teknik lukisan tua, teknik naik perahu, teknik buku kehidupan, teknik karpet ajaib, teknik imajinasi terbimbing, dan teknik mimpi hipnotik.
Sementara teknik dalam strategi berdasar ekspresi motor adalah teknik pendulum, teknik jari, teknik menulis otomatis, dan teknik menggambar otomatis.
Teknik pengungkapan penting dalam hipnoanalisis, selain yang telah dijelaskan di atas, adalah regresi hipnotik dan revivifikasi. Keduanya adalah fenomena yang saling berhubungan dan mewakili derajat respon klien sepanjang kontinum regresi.
Revivifikasi adalah mengalami kembali, saat ini, dalam kondisi hipnosis, pengalaman masa lalu dengan cara yang kuat dan literal (Sheehan dan McConkey, 1982).
Regresi hipnotik lebih kuat dan literal. Walau sering hanya bersifat parsial, regresi hipnotik membawa klien kembali pada fungsi perseptual, kognisi, dan perilaku seturut pengalaman dan emosi yang seturut usia regresi (Reiff dan Sheerer, 1959).
Regresi atau pergerakan mundur dari masa sekarang ke masa lalu, dalam upaya mencari dan menemukan kejadian paling awal yang mendasari simtom, dapat dilakukan melalui dua jalur utama.
Pertama, melalui rangkaian ide saling terhubung, jembatan kognitif (cognitive bridge), yang menghubungkan satu ide dengan ide lain karena terdapat tumpang-tindih antara kedua ide pada satu ide penghubung. Regresi jembatan kognitif dilakukan dalam kondisi sadar normal, namun tidak efektif dalam mengungkap akar masalah.
Kedua, melalui jalur kesamaan afek yang menghubungkan antara satu memori dengan memori lain. Dalam hal ini, afek berlaku sebagai jembatan penghubung (affect bridge). Regresi jembatan afek hanya bisa dilakukan dalam kondisi hipnosis dalam dengan persyaratan tertentu.
Teknik jembatan afek diciptakan dan diujicobakan oleh John Watkins pertama kali di tahun 1958. Artikel ilmiah tentang teknik ini terbit pertama kali dalam bahasa Spanyol (Watkins, 1961), dan selanjutnya dalam bahasa Inggris (Watkins, 1971).
Regresi jembatan afek mengandalkan gambar mental untuk mengakses emosi spesifik, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan bakar regresi (Gunawan, 2008). Ini sejalan dengan yang dinyatakan Singer (1966) bahwa gambar mental dan pengalaman afektif saling terhubung.
Dengan demikian gambar mental adalah sarana langsung untuk mendapatkan akses ke dunia emosi. Gambar mental merupakan teknik pengungkapan sangat efektif karena ia adalah representasi simbolis dari aktivitas dunia internal individu, berbagai emosi bentuk pikiran, dan konflik yang tidak sadari (Reyher, 1963; Shorr, 1972). Gambar mental mengungkapkan arus bawah ini secara jauh lebih jelas daripada pemikiran logis rasional berorientasi pada realitas.
Teknik hipnoanalitik lainnya, yang juga sangat efektif dalam mengungkap akar masalah adalah teknik ego state. Untuk dapat mengerti dan melakukan teknik ego state dengan benar dan efektif butuh pemahaman berdasar landasan teoretik baru.
Teknik ego state bermula dari konsep psikoanalisis yang digagas Federn (1952), dan selanjutnya dielaborasi oleh Weiss (1960). Teori ini menjadi operasional berkat modifikasi dan pengembangan lebih lanjut oleh Watkins (1978), Watkins dan Watkins (1979, 1981, 1982, 1986). Gunawan (2008) mengembangkan lebih lanjut teknik ego state berdasar berbagai informasi yang diperoleh melalui artikel jurnal, dikuatkan dengan temuan di ruang praktik, dan menggunakan nama baru, ego personality.
Satu hal yang sangat perlu dipahami, berbagai artikel jurnal dan literatur lain, pada umumnya mendiskusikan teknik-teknik hipnoanalisis pada tataran konsep. Sangat jarang membahas hingga ke tingkat operasional, menjelaskan langkah demi langkah penerapan di ruang praktik.
Berbagai teknik yang telah dijelaskan di atas, benar efektif dalam mengungkap akar masalah, namun dalam praktik klinis, ini hanya langkah awal. Informasi yang berhasil diungkap, baik berupa kejadian dan juga emosi, perlu diproses menggunakan teknik lanjutan yang tepat, efektif, aman, dan mampu berdampak terapeutik positif, signifikan, dan bertahan lama.

Komponen Sugesti
8 Februari 2022Oleh: Dr. Dr. Adi W. Gunawan, ST., MPd., CCH®
Ada banyak definisi sugesti bergantung pandangan dan pemahaman masing-masing pakar atau praktisi. Saya mendefinisikan sugesti sebagai metode komunikasi bertujuan menghasilkan penerimaan dan pelaksanaan penuh keyakinan atas pesan yang disampaikan, tanpa melibatkan penilaian kritis terhadap alasan penerimaan pesan, dan mengakibatkan perubahan penilaian, pendapat, sikap, dan atau perilaku.
Konsep sugesti dapat didekati melalui beberapa cara. Pertama, melalui metode, cara, atau kanal komunikasi yang digunakan. Bila sugesti ditilik dari cara penyampaiannya, dikenal dua jenis sugesti yaitu heterosugesti, sugesti yang disampaikan seseorang kepada orang lain, dan autosugesti (sugesti intrapersonal) yaitu sugesti yang dilakukan seseorang kepada dirinya sendiri.
Sugesti dapat didekati melalui variabel situasional dan kontekstual. Kondisi aktual saat sugesti diberikan berpengaruh pada kecenderungan sugesti diterima dan dijalankan. Sugesti yang diberikan dalam situasi klinis, di ruang praktik, di laboratorium untuk penelitian, dan di tempat umum berpengaruh pada derajat respon dan nonrespon terhadap sugesti.
Sugesti juga dapat ditilik melalui sumber sugesti, bisa bersifat privat atau publik. Pada umumnya dipahami bahwa sugesti bekerja pada level privat, yaitu satu individu mendapat atau menerima sugesti yang berasal baik dari orang lain atau dirinya sendiri. Di sisi lain, sugesti juga dapat diberikan dan diterima secara kolektif melalui sugesti massal.
Komponen lain sugesti adalah cara ia dilakukan. Ada sugesti berisi pesan jelas, dan ada yang sengaja dibuat tidak jelas. Ada pula berupa sugesti verbal dan nonverbal. Sugesti nonverbal butuh dukungan tambahan fungsi kognisi, terutama penglihatan, guna memastikan pesan yang disampaikan diterima dengan baik dan meningkatkan kecenderungan respon terhadap sugesti.
Sugesti, selain bisa berupa pesan verbal atau nonverbal, juga bisa dalam bentuk pesan visual, baik yang telah dirancang sedari awal atau yang dimunculkan secara spontan saat sugesti diberikan.
Daya (power) sugesti juga berpengaruh terhadap penerima. Sugesti yang diberikan secara lembut akan dipersepsi dan dimaknai berbeda dibanding sugesti yang melibatkan emosi dan diberikan dengan tegas. Respon dari pemberian sugesti ini bisa berupa makna bahwa isi sugesti adalah "permintaan" atau "perintah" untuk dilaksanakan.
Komponen yang berpengaruh besar dan mampu meningkatkan daya sugesti adalah durasi pemberian sugesti. Sugesti yang diberikan secara singkat dan hanya sekali berdampak beda dibanding sugesti diberikan untuk waktu lebih lama dan berulang.
Keefektifan sugesti yang tampak dalam bentuk kecenderungan penerima sugesti melakukan pesan yang disampaikan juga ditentukan atau dipengaruhi oleh karakteristik dan otoritas pemberi sugesti. Semakin tinggi otoritas pemberi sugesti, baik riil atau hanya berdasar persepsi, semakin kuat pengaruh sugesti yang diberikan terhadap penerima.
Tingkat keefektifan sugesti juga dipengaruhi oleh motivasi, kesiapan, dan kesediaan penerima sugesti untuk menerima dan menjalankan sugesti. Semakin tinggi motivasi kesiapan, dan kesediaan semakin mudah sugesti diterima dan bekerja atau dilaksanakan.
Komponen lain dalam sugesti adalah waktu pemberian sugesti (timing), jenis pesan, perhatian, dan pemahaman penerima terhadap pesan yang diberikan.
Sugesti juga dipengaruhi konten aktual dari pesan yang diberikan dan target yang hendak dicapai. Ada sugesti berisi pesan dengan tujuan memengaruhi proses sensori dan mengakibatkan terjadinya distorsi sensori (De Pascalis dan Daddia, 1985; Gheorhiu dan Reyher, 1982), dan ada yang bertujuan memengaruhi proses sesori-motor (Gheorghiu dan Walter, 1989), dan ada pula sugesti yang secara khusus dirancang untuk menarget proses memori (Gudjonsson, 1983; Loftus, 1979).
Dan yang terakhir, dalam konteks klinis, komponen dan determinan penting sugesti diterima dan dijalankan adalah kondisi kesadaran penerima sugesti saat sugesti diberikan. Keefektifan penerimaan sugesti secara umum dapat dikatakan ditentukan oleh kedalamam rileksasi pikiran. Semakin dalam rileksasi pikiran, semakin baik.

Meditasi, Mindfulness, Hipnosis, dan Hipnoterapi
8 Januari 2022Oleh: Dr. Dr. Adi W. Gunawan, ST., MPd., CCH®
Artikel ini bertujuan menjelaskan kesamaan, perbedaan, dan manfaat meditasi, mindfulness, hipnosis dan hipnoterapi.
Hipnosis dan meditasi masing-masing merujuk pada rangkaian luas praktik berasal dari tradisi panjang dalam sejarah dan budaya sangat berbeda. Mereka menggunakan dan melibatkan beragam aktivitas kognisi, afeksi, perilaku, dan bertujuan mencapai sejumlah besar hasil terapeutik dan spiritual, mulai dari analgesia hingga pencerahan (enlightenment).
Praktik meditasi dan mindfulness (perhatian penuh) jauh mendahului pemanfaatan hipnosis untuk tujuan terapeutik, dan dapat ditelusuri hingga lebih dari 2.000 tahun lalu, saat Buddha menjelaskan meditasi sebagai cara melepas kelekatan pada bentuk-bentuk pikiran, perasaan, dan perilaku atau kebiasaan yang sifatnya mengganggu (Lyn dkk, 2006).
Keragaman di antara tujuan dan teknik dalam domain-domain ini mengakibatkan tantangan serius dalam upaya menetapkan definisi inklusif dari praktik masing-masing.
Di luar keragaman aktivitas dalam praktik hipnosis dan meditasi, inkonsistensi interpretasi terhadap istilah utama, seperti hipnosis (Kirsch dkk, 2011) dan mindfulness (Williams dan Kabat-Zinn, 2011) – semakin membuat kabur konsep utama dan menghambat kemajuan penelitian dalam topik ini.
Meditasi biasanya dipahami lebih berdasar efek yang dihasilkannya. Ada yang mendefinisikan meditasi sebagai teknik relaksasi (Benson, 1975). Definisi ini berimplikasi pada kemiripan masalah yang ditemui dalam literatur tentang relaksasi (Davidson dan Schwartz, 1976), yang menyatakan bahwa teknik relaksasi adalah teknik yang menghasilkan efek-efek tertentu, seperti berkurangnya ketegangan otot, dan menurunnya keaktifan sistem saraf simpatik.
Tentunya, cara mendefinisikan meditasi berdasarkan efek yang dihasilkannya, menggunakan variabel dependen untuk mendefinisikan variabel independen, bukanlah cara yang tepat dan memuaskan, dan tidak mampu menghasilkan definisi akurat.
Masalah lain dalam mendefinisikan meditasi adalah terdapat begitu banyak jenis atau teknik meditasi. Ada teknik meditasi yang dilakukan dengan postur tubuh duduk dan menghasilkan kondisi tenang dan rileks (Wallace, Benson, dan Wilson, 1971). Kegiatan meditasi lainnya dilakukan dengan duduk diam dan menghasilkan kondisi gembira dan semangat (Das dan Gastaut, 1955; Croby dkk, 1978).
Sementara teknik lainnya, seperti tarian berputar Sufi, Tai Chi, dan Hatha yoga melibatkan gerakan fisik hingga taraf tertentu (Naranjo dan Ornstein, 1971; Hirai, 1974). Kadang, “meditasi bergerak” ini menghasilkan kondisi gembira, kadang kondisi rileks (Fischer, 1971; Davidson, 1976). Bergantung pada tipe meditasi yang dilakukan, tubuh dapat aktif dan bergerak, atau relatif diam dan pasif.
Walau terdapat banyak teknik, bila dicermati, sejatinya hanya terdapat tiga kelompok besar strategi dan regulasi perhatian yang digunakan dalam meditasi: fokus pada objek spesifik di dalam medan perhatian (meditasi konsentrasi – samatha), fokus pada medan perhatian (meditasi perhatian penuh – vipassana / mindfulness), dan bergeser antara keduanya. Perhatian dalam konteks ini mengacu secara luas pada alokasi sumber daya pemrosesan kognitif.
Pola fokus seperti ini sejalan dengan mekanisme otak dalam memerhati, seperti yang dijelaskan Pribram (1971), serupa dengan kamera dan bekerja dengan dua cara. Pertama, fokus kamera seperti pada lensa sudut lebar – kesadaran luas dan menyapu semua medan perhatian (meditasi mindfulness). Kedua, tipe perhatian serupa dengan lensa tele (zoom), secara spesifik fokus hanya pada segmen terbatas di medan perhatian (meditasi konsentrasi).
Mengacu pada perspektif Buddhis, para ilmuwan secara umum mengelompokkan praktik meditasi ke dalam dua kategori: meditasi konsentrasi /samatha dan meditasi pengamatan terbuka / vipassana (Lutz dkk, 2008).
Meditasi konsentrasi (samatha) atau perhatian terpusat melibatkan konsentrasi pada satu objek spesifik di dalam medan perhatian, seperti napas, mantra atau kalimat doa yang diulang. Sementara meditasi pengamatan terbuka (vipassana) melibatkan perluasan perhatian dengan mengikutsertakan seluruh bidang perhatian dari satu momen pengalaman ke momen pengalaman berikutnya.
Walau pembagian meditasi secara konseptual menjadi dua jenis cukup bermanfaat, banyak praktik meditasi tidak secara tegas masuk ke dalam skema keduanya, seperti praktik meditasi cinta kasih dan visualisasi (Lutz, Dunne, dan Davidson, 2006).
Menggunakan mekanisme perhatian sebagai dasar untuk menetapkan definisi, dapat dinyatakan bahwa meditasi merujuk pada sekumpulan teknik dengan kesamaan berupa upaya sadar dalam mengarahkan dan memusatkan perhatian secara nonanalitikal, dan sebuah upaya sadar untuk tidak larut dalam bentuk-bentuk pikiran dan perasaan yang muncul.
Meditasi Buddhis dan Mindfulness
Ajaran Buddha tentang meditasi perhatian penuh (mindfulness), singkat dan jelas. Ajaran ini tertulis dalam Ānāpānasati sutta dan Satipatthana sutta. Keduanya menjelaskan metode sistematis untuk mengolah dan mengembangkan kesadaran, dengan secara khusus memerhatikan napas masuk dan keluar. Dalam Ānāpānasati sutta, Buddha menyatakan:
[1] Menarik napas panjang, ia menyadari, "Aku sedang menarik napas panjang." Mengembuskan napas panjang, ia menyadari, "Aku sedang mengembuskan napas panjang."
[2] Menarik napas pendek, ia menyadari, "Aku sedang menarik napas pendek." Mengembuskan napas pendek, ia menyadari, "Aku sedang mengembuskan napas pendek."
[3] Ia berlatih sebagai berikut, "Aku akan menarik napas dengan mengalami seluruh tubuh (atau napas)." Ia berlatih sebagai berikut, "Aku akan mengembuskan napas dengan mengalami seluruh tubuh (atau napas)."
[4] Ia berlatih sebagai berikut, "Aku akan menarik napas dengan menenangkan bentukan jasmani." Ia berlatih sebagai berikut, "Aku akan mengembuskan napas dengan menenangkan bentukan jasmani."
(Buddhadasa, 1988, p. 147)
Uraian ini menunjukkan bahwa Buddha memandang napas baik sebagai (1) objek kesadaran (“[1] Menarik napas panjang, ia menyadari, "Aku sedang menarik napas panjang.") dan (2) sarana untuk mengarahkan perhatian (“[3] ] Ia berlatih sebagai berikut, "Aku akan menarik napas dengan mengalami seluruh tubuh (atau napas).").
Praktisi meditasi, dengan demikian, tidak hanya secara berkesinambungan memerhatikan napas, juga memanfaatkan proses ini untuk mengembangkan kesadaran pada berbagai aspek diri sebagai bagian dari latihan mental.
Uraian berikutnya menggambarkan kesadaran perhatian penuh terhadap perasaan dan persepsi ([5] hingga [8]), pikiran dan kehendak ([9] hingga [12]), dan ketidakkekalan fenomena ([13] hingga [16]).
[5] Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan menarik napas dengan mengalami sukacita.” Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan mengembuskan napas dengan mengalami sukacita.”
[6] Ia berlatih sebagai berikut, “‘Aku akan menarik napas dengan mengalami kenikmatan.” Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan mengembuskan napas dengan mengalami kenikmatan.”
[7] Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan menarik napas dengan mengalami bentukan batin.” Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan mengembuskan napas dengan mengalami bentukan batin.”
[8] Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan menarik napas dengan menenangkan bentukan batin.” Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan mengembuskan napas dengan menenangkan bentukan batin.”
[9] Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan menarik napas dengan mengalami pikiran.” Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan mengembuskan napas dengan mengalami pikiran.’”
[10] Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan menarik napas dengan menggembirakan pikiran.” Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan mengembuskan napas dengan menggembirakan pikiran.”
[11] Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan menarik napas dengan mengonsentrasikan pikiran.” Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan mengembuskan napas dengan mengonsentrasikan pikiran.”
[12] Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan menarik napas dengan membebaskan pikiran.” Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan mengembuskan napas dengan membebaskan pikiran.”
[13] Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan menarik napas dengan merenungkan ketidakkekalan.” Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan mengembuskan napas dengan merenungkan ketidakkekalan.”
[14] Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan menarik napas dengan merenungkan peluruhan.” Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan mengembuskan napas dengan merenungkan peluruhan.”
[15] Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan menarik napas dengan merenungkan lenyapnya.” Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan mengembuskan napas dengan merenungkan lenyapnya.”
[16] Ia berlatih sebagai berikut, ”Aku akan menarik napas dengan merenungkan lepasnya.” Ia berlatih sebagai berikut, “Aku akan mengembuskan napas dengan merenungkan lepasnya.”
Berdasar mekanisme perhatian yang terlibat dalam meditasi, secara ringkas meditasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan membawa pikiran dengan penuh kesadaran pada satu objek tertentu (Paññāvaro, 2016). Sementara menurut Wise (2009) meditasi adalah kondisi kesadaran dengan pola gelombang otak sangat spesifik. Kondisi meditatif ini dicapai dengan teknik sesuai.
Dalam meditasi, perhatian dapat secara aktif diarahkan pada satu objek konsentrasi dengan mengabaikan objek lainnya (Anand, Chinna, dan Singh, 1961). Perhatian juga dapat fokus pada satu objek, tetapi saat objek lain, bentuk-bentuk pikiran, atau perasaan muncul, mereka dapat dikenali sejenak, kemudian perhatian diarahkan kembali pada objek semula, seperti dalam meditasi vipassana dan transendental. Perhatian juga dapat tidak difokuskan eksklusif pada objek tertentu, seperti dalam Zen Shikan Taza (Kasamatsu dan Hirai, 1966; Krishnamurti, 1979).
Mindfulness adalah sebuah kata, digunakan dalam banyak cara. Definisinya bergantung pada siapa yang menggunakannya dan dalam konteks apa. Mindfulness adalah terjemahan dari bahasa Pali sati, Sansekerta smrti, Mandarin nian, dan Tibet dran pa, bermakna kesadaran (awareness), perhatian (attention), dan pengingatan (remembering) (Germer, 2004).
Mindfulness adalah satu bentuk meditasi Buddhis yang berakar pada tradisi Theravada di Asia Tenggara. Walau istilah mindfulness telah banyak digunakan, hingga saat ini belum ada konsensus definisinya di antara para peneliti karena keragaman prosedural dan kompleksitas fenomenologis terkait praktik mindfulness (Lifshitz et al., 2012; Otani, 2016; Pekala & Creegan, 2020).
Konsep mindfulness (perhatian penuh) mulai populer di Barat sejak Jon Kabat-Zinn (1991, 1994) mengembangkan teknik reduksi stres berbasis mindfulness (mindfulness-based stress reduction).
Nyanaponika (1972) mendefinisikan mindful sebagai kesadaran jernih dan tunggal akan apa yang terjadi pada dan di dalam diri pada momen-momen persepsi berkelanjutan.
Kabat-Zinn (1990/2005) mendefinisikan mindfulness sebagai perhatian yang dilakukan secara sadar, tanpa menilai atau menghakimi, terhadap pengalaman dari satu momen ke momen berikutnya.
Mindful menurut Paññavaro (2016) adalah pengamatan atas pengalaman dan bagaimana pengalaman ini berlangsung tanpa memberi makna, menghakimi, menilai, memberi nama atau label, melibatkan emosi, atau berusaha dengan sesuatu cara mengubah pengalaman ini.
Ada dua tipe mindfulness: (1) samatha, menggunakan perhatian terfokus pada objek spesifik dan (2) vipassana yang menekankan pengamatan terbuka terhadap persepsi yang berlangsung.
Dalam perhatian tidak menghakimi, netral, apa adanya, mindfulness mencakup penerimaan, kesabaran, dan toleransi terhadap timbul tenggelam bentuk-bentuk pikiran, perasaan, sensasi yang muncul di dalam kesadaran, atau memerhatikan konten kesadaran, sebagaimana dalam meditasi vipassana atau meditasi pandangan terang (Mellinger dan Lynn, 2012).
Meditator, dalam melakukan praktik meditasi mindfulness, memfokuskan perhatiannya pada objek yang telah ditentukan sebelumnya, misal napas, gerakan perut, suara tertentu, gambaran mental di pikiran, sambil tetap memerhatikan stimuli eksternal (penglihatan, suara, bau, sentuhan, dll) dan internal (misal bentuk pikiran yang muncul, perasaan, dll) rangsangan pada saat bersamaan.
Inti praktik mindfulness bukan sekadar memusatkan perhatian pada napas, seperti yang diyakini orang awam, melainkan penerimaan dan pelepasan berkelanjutan dari berbagai fenomena seperti suara-suara dari lingkungan, suara atau dialog internal, bentuk-bentuk pikiran atau emosi, dan sensasi fisik.
Hipnosis dan Hipnoterapi
Dalam konteks hipnosis dan hipnoterapi, terdapat dua pikiran: pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Fungsi pikiran sadar mengidentifikasi informasi yang masuk melalui enam indera, membandingkan informasi ini dengan data di pikiran bawah sadar, melakukan analisis, dan membuat keputusan.
Fungsi pikiran bawah sadar adalah tempat menyimpan data atau memori jangka panjang, menyimpan hal-hal yang tidak tertangkap oleh pikiran sadar, tempat tiga jenis kebiasaan, emosi, kepribadian, intuisi, kreativitas, persepsi, keyakinan (belief), dan nilai hidup (value). Pengaruh dan kontribusi pikiran sadar pada diri individu berkisar antara 1% hingga 5%, sementara pikiran bawah sadar antara 95% hingga 99% (Gunawan, 2012).
Pikiran sadar mampu memproses hingga 40 bit informasi tiap detik (Zimmermann (1989). Sementara menurut Trincker (dalam Norrentranders, 1998:126) pikiran bawah sadar mampu memproses hingga 40.000.000 bit informasi tiap detik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbandingan kapasitas pemrosesan data antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar adalah 40 bit/detik berbanding 40.000.000 bit/detik atau 1 berbanding 1.000.000.
Seturut dengan keberadaan dua pikiran, terdapat dua logika pikiran: logika pikiran sadar (conscious logic) dan logika pikiran bawah sadar (trance logic). Kedua logika pikiran ini bekerja dengan keunikan dan hukum berbeda.
Hipnosis adalah kondisi kesadaran bercirikan pikiran sadar fokus dan rileks, berakibat pikiran menjadi sangat reseptif menerima pesan-pesan mental yang disampaikan, baik berupa pesan verbal dan atau visual. Kondisi pikiran sadar rileks ini bisa diikuti, namun tidak selalu, dengan kondisi tubuh fisik rileks (Gunawan, 2018).
Kondisi hipnosis bisa dicapai atau terjadi melalui beberapa cara: swahipnosis, heterohipnosis, autohipnosis, dan parahipnosis. Swahipnosis adalah hipnosis yang dilakukan seseorang pada dirinya sendiri. Heterohipnosis adalah hipnosis yang dilakukan seseorang pada orang lain, terutama dalam konteks klinis. Autohipnosis adalah hipnosis yang terjadi dengan sendirinya saat individu berada dalam situasi atau kondisi tertentu. Dan parahipnosis adalah hipnosis akibat obat.
Berbeda dengan pehamahan awam, kondisi hipnosis bukan tidur atau kondisi tak sadar. Dalam kondisi hipnosis, individu tetap sadar sepenuhnya dan memiliki kendali penuh atas dirinya.
Dalam kondisi hipnosis individu melepas kendali atas fungsi kritis pikirannya, lepas dari fungsi pengawasan kekinian pengalaman, dan teregresi ke proses berpikir primer di mana terdapat kebebasan dan keleluasaan pikiran dalam memunculkan berbagai bentuk gambaran mental, daya khayal, menerima segala sesuatu yang sebelumnya tidak rasional menjadi rasional, dan individu mengalami fenomena trance logic (Orne, 1959).
Terdapat banyak lapis kesadaran atau jenjang kedalaman, kondisi hipnosis. Mulai dari kedalaman dangkal (light trace), kedalaman menengah (medium trance), kedalaman dalam (deep trance), hingga kedalaman ekstrim (extreme depth). Setiap kedalaman bercirikan fenomena spesifik baik di aspek mental maupun fisik.
Terdapat lebih dari dua puluh skala kedalaman hipnosis. Skala paling awal adalah Magnetic Scale (Liébeault, 1866, 1889). Sementara skala yang populer digunakan sebagai acuan adalah Stanford Scales of Hypnotic Susceptibility, Forms A and B, Stanford Scales of Hypnotic Susceptibility, Form C, dan Stanford Profile Scales of Hypnotic Susceptibility (Weitzenhoffer dan Hilgard, 1959, 1962, 1963, 1967), dan Harvard Group Scales of Hypnotic Susceptibility, Forms A dan B (Shor dan Orne, 1962). Di tahun 2010, di Indonesia telah disusun AWG Hypnotic Depth Scale yang digunakan sebagai acuan dalam proses hipnoterapi oleh hipnoterapis klinis anggota Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia (AHKI).
Hipnosis per se tidak terapeutik, karena ia hanya kondisi kesadaran. Manfaat yang bisa dirasakan bila seseorang mengalami kondisi hipnosis adalah terjadinya relaksasi pikiran sadar dan tubuh fisik. Ini menghasilkan respon relaksasi yang berdampak baik untuk ketenangan dan kesehatan. Namun, bila tujuan yang ingin dicapai adalah kebaikan dan kesejahteraan mental pada tataran lebih luas, hipnosis perlu disandingkan dengan seperangkat teknik atau strategi terapi. Gabungan antara kondisi hipnosis dan teknik terapi dinamakan hipnoterapi.
Secara ringkas, hipnoterapi adalah terapi, bisa menggunakan teknik apa saja, dilakukan dalam kondisi hipnosis. Terapi bisa dilakukan baik oleh diri sendiri, atau oleh terapis pada klien dengan tujuan mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan klien.
Terdapat tiga mazhab hipnoterapi. Pertama, mazhab pantai timur Amerika yang hanya mengutamakan dan menggunakan sugesti sebagai sarana untuk mencapai perubahan. Kedua, mazhab pantai barat Amerika, mengutamakan hipnoanalisis bertujuan mencari, menemukan, dan memroses tuntas akar masalah. Dan ketiga, mazhab eklektik-integratif, dikembangkan oleh AWGI, bercirikan pemanfaatan, integrasi teknik serta pendekatan terapi terkini dan terbaik, bertujuan mencari, menemukan, dan memroses tuntas akar masalah dalam upaya membantu individu mengalami perubahan positif dengan aman, efektif, cepat, mudah, menyenangkan, dengan hasil terapi bertahan lama.
Proses perubahan transformatif dan dampak terapeutik positif terjadi saat terapis berhasil membantu klien mencapai pengalaman emosional korektif (Alexander dan French, 1946) melalui rekonstruksi memori patologis (Watkins, 1978).
(Bangun) memori hanya bisa direkonstruksi bila ia telah lentur setelah beberapa prasyarat terpenuhi, terutama setelah terjadi peluruhan emosi dan pemanfaatan trance logic. Tanpanya, bangun memori akan tetap kokoh, rigid, dan tidak bisa direkonstruksi untuk kebaikan dan kesembuhan klien (Gunawan, 2018).
Upaya pemulihan kesejahteraan mental dan emosi klien pascakejadian traumatik dilakukan dengan menggunakan teknik khusus, di kedalaman hipnosis dalam (profound somnambulism) tanpa mengganggu integritas memori (traumatik).
Dibutuhkan pemahaman mendalam tentang landasan teori dan cara kerja memori agar bisa melakukan rekayasa dan rekonstruksi memori patologis secara aman dan tepat sasaran. Tanpa pemahaman benar hipnoterapis bisa salah dalam melakukan atau justru menolak melakukan rekonstruksi memori.
Kesadaran
Kesadaran (consciousness) memiliki lima komponen: kondisi kesadaran (state of consciousness), isi kesadaran (content of consciousness), kesadaran (awareness), energi, dan struktur.
Kesadaran (consciousness) dibedakan menjadi dua kelompok: kesadaran normal (baseline state of consciousness) dan kesadaran berbeda (discrete state of consciousness). Kesadaran normal adalah kesadaran yang dialami individu dalam kondisi bangun, sadar normal. Sementara kesadaran berbeda adalah semua kondisi kesadaran di luar kelompok kesadaran normal. Kesadaran berbeda sering disebut sebagai altered state of consciousness (ASC). Kondisi meditatif dan kondisi hipnosis adalah kondisi kesadaran berbeda.
Menurut Tart (1975) kondisi kesadaran distabilkan oleh empat proses: loading stabilization (stabilisasi beban), negative feedback stabilization (stabilisasi umpan balik negatif), positive feedback stabilization (stabilisasi umpan balik positif), dan limiting stabilization (stabilisasi penghambat).
Isi kesadaran (content of consciousness) adalah muatan yang keluar dari pikiran bawah sadar dan atau nirsadar, naik ke permukaan dan masuk ke wilayah pikiran sadar sehingga dikenali dan diketahui. Setiap kondisi kesadaran merupakan jalur bagi pikiran bawah sadar dan atau nirsadar untuk mengeluarkan muatannya sesuai dengan kondisi psikis, kebutuhan, kesiapan, dan izin dari sistem ego.
Kesadaran (awareness) adalah kemampuan untuk mengetahui atau mengenali atau memikirkan bahwa sesuatu sedang terjadi. Sedangkan kesadaran diri (self awareness) adalah kesadaran akan kondisi sadar. Tingkat kesadaran diri yang tertinggi adalah saat terjadinya perpisahan antara kesadaran dan konten.
Kesadaran (awareness) merujuk pada pengetahuan dasar bahwa sesuatu sedang terjadi, mengamati, atau merasakan. Kesadaran (consciousness) umumnya merujuk pada awareness dalam hal yang jauh lebih rumit. Consciousness adalah awareness yang dipengaruhi oleh struktur pikiran.
Energi dalam hal ini merujuk pada perhatian atau kesadaran (awareness) dalam konteks bahwa suatu struktur yang sebelumnya tidak berpengaruh terhadap kesadaran dapat diaktifkan bila dibutuhkan.
Sementara yang dimaksud dengan struktur, lebih tepatnya struktur psikologis, adalah organisasi yang relatif stabil dari komponen yang menjalankan satu atau lebih fungsi psikologis tertentu. Beberapa struktur membutuhkan energi dalam jumlah tertentu agar dapat bekerja optimal, beroperasi, dihambat kerjanya, diubah, dan atau didestrukturisasi (Tart, 2001).
Bila ditilik dari kesadaran individu saat melakukan meditasi dan dalam kondisi hipnosis, terdapat kemiripan dan perbedaan. Walau individu yang melakukan meditasi maupun yang sedang mengalami kondisi hipnosis tampak sama tenang dan pasif, aktivitas kesadaran mereka sangat berbeda.
Terdapat dua aspek kesadaran dalam konteks mindfulness: perhatian (attention) dan kesadaran (awareness). Perhatian (attention) adalah proses pemusatan kesadaran, memberikan kepekaan yang tinggi pada rentang pengalaman terbatas (Westen, 1999). Kesadaran (awareness) berfungsi sebagai radar bagi kesadaran (consciousness), yang secara kontinu memonitor lingkungan di luar dan di dalam diri individu (Brown & Ryan, 2003). Kesadaran dan perhatian saling terhubung. Perhatian terus-menerus menarik "sosok" keluar dari "tanah" kesadaran, menahan mereka secara fokus untuk jangka waktu yang berbeda-beda.
Hal ini memungkinkan individu untuk dapat menyadari suatu stimulus tanpa harus meletakkan stimulus tersebut sebagai pusat perhatian. Misalnya, ketika seseorang sedang berbincang-bincang, namun tetap menyadari apa yang terjadi di lingkungannya. Sementara attention diartikan sebagai suatu proses memfokuskan kesadaran yang disadari (focusing conscious awareness) dengan cara meningkatkan kepekaan terhadap lingkup pengalaman-pengalaman yang terbatas.
Dari dua tipe meditasi, samatha, mengembangkan kondisi tercerap, adalah praktik mindfulness yang memiliki kemiripan dengan kondisi hipnosis. Samatha, bila dilatih secara konsisten, menuntun pada kondisi konsentrasi terpusat yang dikenal sebagai samadhi atau tercerap sepenuhnya pada objek.
Dalam meditasi samatha, pikiran sadar meditator tercerap, fokus, dan terkunci pada objek seperti napas. Sementara dalam hipnosis, pikiran sadar individu fokus pada suara, tuntunan terapis, sensasi fisik, dan pengalaman yang diungkap pikiran bawah sadar.
Walau terdapat kesamaan, mindfulness dan hipnosis berbeda dalam mekanisme kognitif dan neurofisiologis tertentu. Hipnosis dapat menimbulkan atau meningkatkan disosiasi (mis: amnesia, depersonalisasi, kehilangan sensorik, dll.), bersama dengan pundarnya orientasi realitas umum (generalized reality orientation / GRO) (Shor, 1959).
GRO adalah kerangka referensi internal yang stabil, berfungsi mengarahkan seseorang untuk dapat bernavigasi dengan baik dan terarah, dalam ruang dan waktu, bahkan saat ia tidak secara khusus dan saksama memerhatikan keadaan sekelilingnya (Shor,1959).
Sementara menurut Bruner (1973) GRO adalah skema kognitif yang bekerja atau aktif di latar belakang kesadaran yang memungkinkan seseorang untuk pergi “melampaui informasi yang diperoleh” pada setiap momen untuk mempertahankan orientasinya terhadap realita.
GRO adalah fungsi pikiran yang mengawasi keadaan sekeliling. GRO tidak bekerja saat individu tidur. Dalam hipnosis, tingkat keaktifan GRO bergantung pada kedalaman hipnosis yang berhasil dicapai. Semakin dalam kondisi hipnosis, fungsi GRO semakin pudar.
Dalam praktik mindfulness, khususnya vipassana, praktisi tetap sadar akan pengalaman eksternal dan internal. Bentuk-bentuk pikiran yang mengganggu dan sensasi sakit dikenali namun tidak diberi perhatian, bukan "terputus" seperti dalam disosiasi hipnotik. Perbedaan ini telah terkonfirmasi secara empiris (Lau et al., 2006).
Ciri-ciri kognitif dan fenomenologis yang unik untuk mindfulness dan hipnosis mengindikasikan mekanisme neurofisiologis spesifik yang mendasarinya. Keduanya sangat berbeda dalam konektivitas fungsional di otak.
Dalam hipnosis, fungsi pemantauan terputus dari fungsi eksekutif (Egner, Jamieson, & Gruzelier, 2005). Proses ini yang diperkirakan mengakibatkan terjadinya penghentian sementara dari fungsi penilai kritis terhadap realita, dalam hal ini GRO, dan memungkinkan sugesti hipnotik dan rekonstruksi memori dapat terjadi.
Pada kondisi hipnosis dalam, walau fungsi GRO dan analitis logis menurun atau sangat berkurang, individu tetap dalam kondisi sadar penuh sehingga masih dapat mengendalikan diri sepenuhnya. Ia dapat memutuskan keluar dari kondisi hipnosis seturut keinginannya, kapan pun.
Dalam mindfulness (vipassana), yang terjadi adalah pola sebaliknya. Fungsi pemantauan dan fungsi eksekutif tetap aktif dan terhubung satu dengan lainnya, yang mengakibatkan kesadaran praktisinya meningkat, tidak mengalami penurunan seperti dalam kondisi hipnosis (Lynn, Malaktaris, Maxwell, Mellinger, & van der Kloet, 2012).
Mencermati temuan ini, beberapa ilmuwan neurosains menegaskan bahwa pernyataan Buddha tentang "tercerahkan sepenuhnya" pada saat pencerahan bukan sekadar metafora (Britton, Lindahl, Cahn, Davis, & Goldman, 2014).
Keterhubungan antara fungsi pemantauan, fungsi eksekutif, dan konektivitas otak yang mengalami peningkatan mengatur emosi dan perenungan mendalam yang dilakukan praktisinya (Brewer et al., 2011).
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa mindfulness adalah serangkaian prosedur kognitif yang beragam memfasilitasi perhatian terpusat (samatha) atau pengawasan terbuka tanpa menghakimi (vipassana). Samatha menyerupai hipnosis dengan peningkatan dalam konsentrasi dan pencerapan. Sementara vipassana berbeda dengan hipnosis karena ia meningkatkan, tidak meredupkan kesadaran.
Terapi Berbasis Mindfulness
Mindfulness dapat digunakan baik secara mandiri atau diintegrasikan ke dalam teknik atau pendekatan terapi untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan mental dan emosi.
Saat ini telah dikembangkan pendekatan terapeutik berbasis mindfulness seperti mindfulness based stress reduction (MBSR; Kabat-Zinn, 1990) dan mindfulness-based cognitive therapy (MBCT; Segal, Williams, dan Teasdale, 2002) merujuk pada tradisi mindfulness Buddhis sebagai sumber utama dan inspirasi.
Keefektifan dan manfaat mindfulness dalam konteks klinis terletak pada kemampuan kesadaran memutus response set yang mengendalikan diri individu. Response set adalah pola asosiasi terkondisi yang memfasilitasi pola perilaku, pola pikir, dan respon individu terhadap stimulus atau situasi tertentu. Response set dapat diaktifkan baik oleh stimuli internal maupun eksternal, seperti sugesti dan beragam sinyal yang berasal dari lingkungan.
Mindfulness dapat memutus respon perilaku otomatis yang selama ini menguasai diri seseorang, baik disadari atau tidak, dan membuat individu menjadi sadar akan pola perilaku maladaptif yang ia alami atau lakukan.
Pelatihan mindfulness pada klien akan memampukan klien menyadari dan menangkap pola perilaku yang relatif otomatis dan reaktif menjadi respon yang lebih terkendali (Teasdale, Segal, dan Williams, 2003).
Individu terlatih dalam mindfulness mampu menyadari keberadaan pengalaman atau memori, baik bermuatan emosi negatif maupun emosi positif intens, melihat apa adanya pengalaman ini, tanpa menghakimi, berupaya mengubah, memberi makna, atau masuk ke dalamnya. Melalui pengalaman meditatif, individu tidak hanya mampu menyadari keberadaan fenomena, ia juga menyadari bahwa fenomena-fenomena ini bersifat tidak kekal.
Saat fenomena berupa memori, bentuk pikiran, atau perasaan muncul ke permukaan, sejalan dengan hukum ketidakkekalan, setelah bertahan beberapa saat mereka akan padam dengan sendirinya. Muncul, bertahan, dan padamnya fenomena ini terjadi tidak hanya sekali tapi berulang kali. Setiap kali individu berhasil (hanya) menyadari keberadaan fenomena ini, saat mereka muncul, bertahan sesaat, dan padam, tanpa ia bereaksi atau larut ke dalamnya, setiap kali ini pula terjadi peluruhan emosi dan daya cengkeram fenomena terhadap diri individu, hingga akhirnya response set menjadi nonaktif, dan individu terbebas dari masalah.
Dengan mindfulness, kekuatan perhatian (sati), individu mampu senantiasa membawa batinnya ke saat ini, dan memperlambat arus informasi yang masuk melalui enam indera, dan mendeteksi setiap pengalaman yang berhubungan dengan enam indera, mengetahui mana yang baik / buruk, bermanfaat / merugikan dan menggunakan kebijaksanaan untuk menentukan respon.